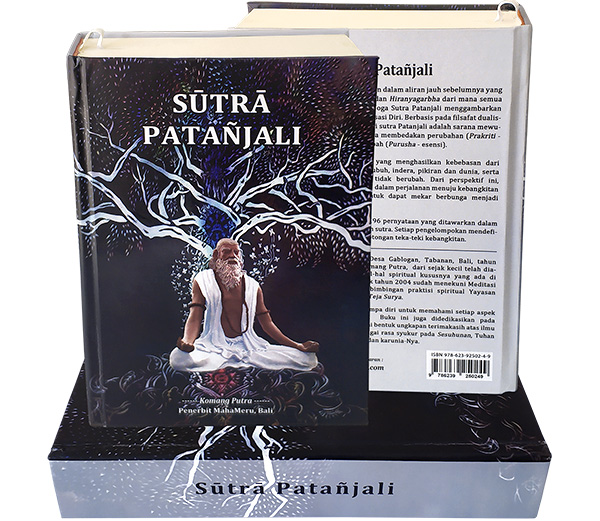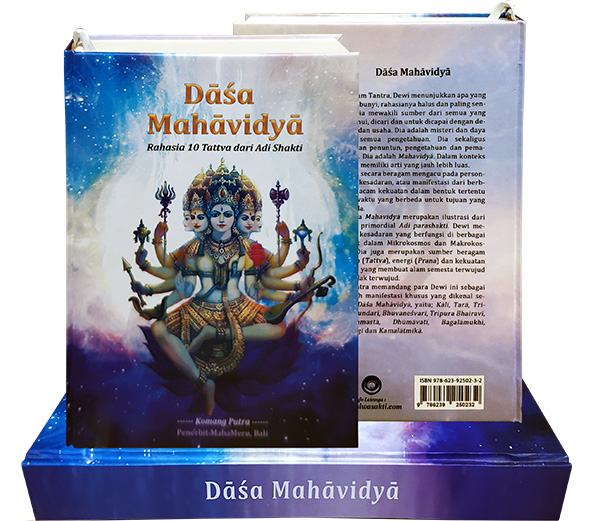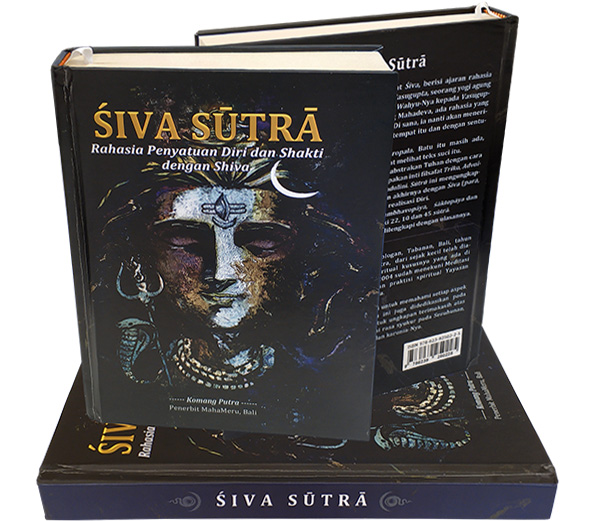Penolakan KARI terhadap Agama Hindu Bali
Pada awal 1950-an para intelektual organik Bali berhadapan dengan politik Islam dalam KARI, yang hanya mengakui keberadaan Islam dan Kristen sebagai agama karena sudah memiliki nabi dan kitab suci, sedangkan agama Hindu yang tidak memilikinya hanya disebut sebagai aliran kepercayaan (Howe 2001:147).
Para intelelektual organik Bali mencoba mencari jalan keluar dengan menerjemahkan Tuhan Yang Maha Esa menjadi Ida Sang Hyang Widhi. Akan tetapi upaya itu tidak berhasil melunakkan hati KARI. Mereka ingin memperoleh penjelasan secara utuh tentang agama Bali. Pada 28 Desember 1950, utusan KARI datang ke Bali untuk mengajukan pertanyaan tentang nama agama, filsafat dan kepercayaan ketuhanan, keberadaan sekolah agama, dan nama kitab suci dan ritual. Pertanyaan yang menyangkut ritual terdiri dari pengertian bersembahyang pada hari purnama dan tilem, persembahyangan di kemulan, pemerajan, dan pura (Anandakusuma, 1966:84-85).
Semua pertanyaan utusan KARI dijawab satu persatu oleh I Gusti Bagus Sugriwa. Ia menjelaskan agama Hindu Bali tidak berbeda jauh dengan agama-agama yang sudah memperoleh pengakuan KARI (Anandakusuma, 1966:84- 85; Stuart-Fox, 1991:35). Utusan KARI juga bertanya tentang kesulitan-kesulitan umat Hindu Bali. I Gusti Bagus Sugriwa menyebutkan ada empat macam kesulitan umat Hindu Bali, yaitu, persoalan biaya upacara dan perbaikan pura, biaya penterjemahan kitab-kitab suci, tunjangan hidup untuk para pedanda dan pemangku, dan tidak adanya perwakilan umat Hindu dalam kantor-kantor urusan agama KARI. Sugriwa meminta supaya semua kesulitan itu segera ditangani oleh KARI (Anandakusuma, 1966:85).
Pembicaraan antara Sugriwa dan utusan KARI berkembang menjadi wacana yang sangat menakutkan para intelektual organik sehingga mendorong mereka untuk mendirikan organisasi-organisasi keagamaan. Sebelumnya hanya ada sebuah organisasi keagamaan, yakni Paruman Para Pandita yang berdiri pada 9 Januari 1949.
Pada 31 Desember 1950, tiga hari setelah kedatangan perwakilan KARI, muncul Majelis Hinduisme, yang berazaskan Hinduisme. Pada awal 1951 muncul organisasi Wiwadha Shastra Sabhha, yang tujuannya untuk mempelajari dan mendiskusikan naskah- naskah agama. Pada pertengahan 1951 muncul organisasi Panti Agama Hindu Bali, di Singaraja. Organisasi ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang filsafat agama Hindu Bali, menyederhanakan upacara agama Hindu Bali, dan mengubah adat istiadat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Pada 10 Juni 1951 para pimpinan organisasi keagamaan mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan hasil pertemuan antara I Gusti Bagus Sugriwa dengan perwakilan KARI. Mereka sepakat untuk mengirimkan mosi (keputusan rapat) kepada Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta, anggota parlemen yang beragama Hindu dengan permintaan supaya ikut membela; dan Gubernur Sunda Kecil di Singaraja dengan permohonan untuk mendapat perhatian (Anandakusuma, 1966:85-86).
Mosi itu berisi empat tuntutan, yaitu penempatan wakil-wakil agama dalam kantor-kantor agama, pembentukan panitia penyusunan kitab ajaran agama Hindu Bali, tunjangan biaya hidup untuk para pedanda dan pemangku, dan sumbangan dana antara lain untuk keperluan upacara keagamaan, pemeliharaan pura-pura utama, dan memajukan kesenian. Keempat tuntutan ditolak oleh KARI (Anandakusuma, 1966:85-87).
Penolakan KARI atas tuntutan para intelektual organik Bali, dipertegaskan oleh sikap Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi Sunda Kecil. Mereka tetap mempertahankan susunan personalia KUA Provinsi Sunda Kecil yang mayoritas beragama Islam. Para intelektual organik Bali menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan kondisi keagamaan di Provinsi Sunda Kecil. Akan tetapi, pimpinan KUA Propinsi Sunda Kecil tidak menghiraukan keluhan yang disampaikan para intelektual organik.
Melihat kondisi di atas, I Made Wedastera Suyasa beradu argumentasi dengan Sekretaris Jendral KARI mengenai status agama Bali. Ia mengkritik cara kerja pejabat KARI dan menuduh mereka tidak mengetahui, bahwa semua agama di Indonesia mempunyai kepercayaan yang mutlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wedastera Suyasa juga membicarakan cita-cita politik RI. Ia berpendapat, cita-cita politik RI yang berdasarkan ketuhanan harus dengan tegas membedakan antara negara dan agama. Persoalan agama, menurut Wedastera Suyasa, bukan urusan negara. Negara harus menjadi pelindung agama berdasarkan keadilan dan pengawasan, supaya semua manusia yang beragama di Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan perasaan tentram.
Reaksi Terhadap Wacana Pendirian Negara Islam Indonesia
Memasuki tahun 1953, bersamaan dengan perjuangan memperoleh pengakuan agama Bali, muncul pula wacana berdirinya Negara Islam. Indikasinya terungkap dalam Rubrik Obor Mimbar Indonesia 3 Januari 1953. Wacana pendirian Negara Islam Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan intelektual organik Bali. Hal itu dapat dilihat dari reaksi I Gusti Bagus Sugriwa pada 20 Februari 1953. Ia berpendapat, dalam azas undang-undang negara RI, tidak tercantum sebutan agama, melainkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan sebutan itu, menurut Sugriwa, semua agama diwilayah RI sudah termasuk di dalamnya.
Reaksi para intelektual organik Bali terhadap wacana negara Islam, ditanggapi oleh seorang intelektual organik Islam, K.H. Abdul Wahab. Ia berpendapat, Nasionalisme adalah kebangsaan yang berisikan agama, contohnya di Pakistan dan Arab. Redaktur Bhakti menanggapi pernyataan itu, bahwa nasionalisme adalah kebangsaan dan tidak benar jika isinya agama, apalagi agama Islam. Nasionalisme dan agama harus dipisahkan, sebab Indonesia bukan Pakistan maupun Arab. Bhakti mengakui, umat Islam di Indonesia memang mayoritas, namun kebesarannya tidak bulat, karena itu harus dipilih antara agama atau nasionalisme. Agama dan nasionalisme tidak mungkin dipersatukan, sebab masing- masing mempunyai pengaruh dan pegangan yang kuat pada diri manusia.
Artikel Bhakti menjadi pemicu perdebatan antara intelektual organik Bali melawan sesamanya dari kalangan Islam politik. Pada 1 Februari 1954, seorang intelektual organik Islam dari Jakarta menulis sebuah artikel dalam Bhakti, yang berisikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Seorang intelektual organik KARI menyatakan setuju dengan pendapat Bhakti maupun Abdul Wahab, karena masing- masing menyoroti persoalan dari sudut agama masing-masing. Pangkal persoalannya, karena memang ada perbedaan isi dan jiwa antara Islam dan Hindu Bali. Dalam Qur’an dan Sabda yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, diatur soal-soal kenegaraan dan kemasyarakatan, sedangkan dalam Hindu Bali tidak. Oleh karena itu, menurut intelektual organik KARI, dalam konsepsi Islam, Nasionalisme dan Islam tidak dapat dipisahkan.
Pada bulan Maret 1954, Sutrisna Sangging, seorang intelektual organik Bali melibatkan diri dalam perdebatan. Ia tidak sepakat dengan argumentasi intelektual organik KARI, karena dianggap bertentangan antara isi dengan jiwanya, karena mereka belum mampu memahami perbedaan antara Universalisme, Internasionalisme, dan Nasionalisme.
Pendapat Sutrisna Sangging di atas, didukung oleh majalah Bhakti, yang berpendapat, bahwa “umat Islam belum memiliki kesatuan pandang tentang Nasionalisme dan agama”. Menurut Bhakti, orang Islam sudah melewati batas-batas nasionalisme, karena mereka hanya dapat berdekatan melalui agama. Orang-orang Islam, menurut Bhakti, menyebut orang lain sebagai kafir sekalipun satu kebangsaan, hanya karena berbeda agama.
Menyangkut persoalan Pancasila, perdebatan dipicu oleh pernyataan Bhakti 17 Oktober 1953, yang antara lain menyebutkan, bahwa tanpa Pancasila makna kemerdekaan Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pancasila, dalam pandangan Bhakti, dapat menjamin ke- sejahteraan individu, membentuk dan membina masyarakat yang adil dan makmur, mengembangkan kebudayaan Bali, serta menghidupkan ekonomi rakyat dan keadilan sosial. Pendapat ini ditanggapi oleh intelektual organik KARI pada Februari 1954, bahwa umat Islam pasti tidak akan menghilangkan Pancasila, melainkan hanya menginginkan pelaksanaannya dilakukan secara konsekuen. Dalam pandangan intelektual organik KARI, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, mempunyai konsekuensi bahwa pedoman undang-undang, peraturan, dan hukum negara seharusnya berdasarkan firman dan sabda Tuhan Yang Maha Esa.