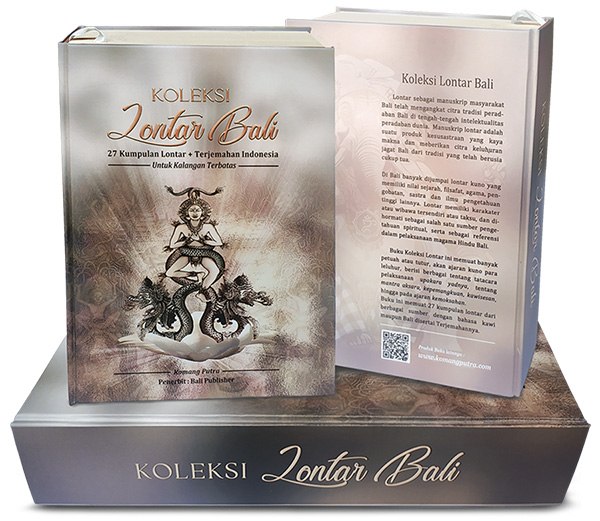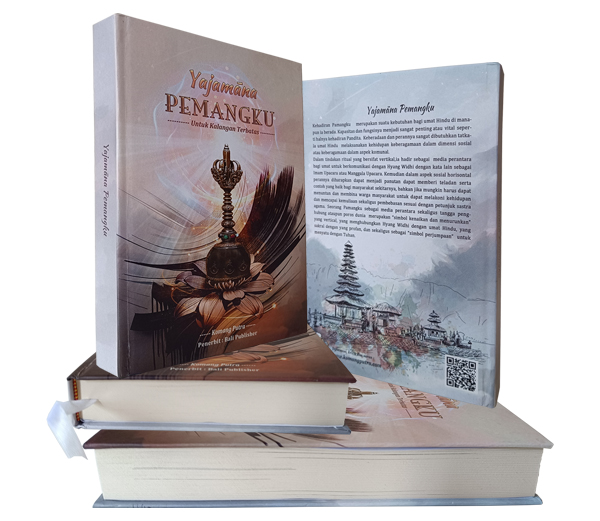Bali dulunya dikenal di masyarakat memeluk Agama Tirta sebelum dikenal dengan Hindu Dharma. Sekte Animisme yang disebut Bali Mula, telah ada dan berkembang pada masa Warmadewa. Agama Hindu Bali merupakan sinkretisme (penggabungan) kepercayaan Hindu aliran Siwa, Waisnawa dan Brahma, dengan kepercayaan asli (local genius) suku Bali. Karena adanya pergolakan, akhirnya diadakan paruman yang disebut Bata Anyar. Pertemuan tersebut dilakukan di Pura Samuan Tiga yang dipimpin Empu Kuturan.
Pertemuan tersebutlah yang menjadi tonggak awal lahirnya tatanan berkeagamaan dan berkehidupan di Pulau Bali dengan dasar penyatuan dari semua sekte yang ada.
Namun kini kenyataannya lebih kompleks dari Hindu Veda secara Universal. Bali telah kian banyak mengalami import ajaran India, tidak saja melalui pengaruh Majapahit yang menyebar melalui rumah-rumah individu juga pada para Brahmana. Indianisasi ini nyaris sudah menyentuh ritual dan yadnya. Pengaruh utamanya ditemukan dalam penerapan prinsip reinkarnasi, meskipun orang Bali bereinkarnasi di antara kerabat mereka.
Tidak ada batas konseptual yang tepat yang memisahkan apa yang asli, di mana pemujaan leluhur adalah yang utama, dari apa yang dimuat dalam aturan kosmogoni India. Kedua tradisi saling terkait. Namun, klasifikasi Bali baru-baru ini sebagai masyarakat yang secara resmi beragama Hindu Dharma saat ini mengarah pada “hinduisasi” kepercayaan.
Bali berada di persimpangan dua tradisi: tradisi warisan Nusantara (Bali), ditandai oleh penyembahan leluhur, dan tradisi India klasik, di mana gagasan kosmisitas berlaku, makrokosmos di satu sisi, dan di sisi lain mikrokosmos makhluk hidup.
Sehubungan dengan dua komponen ini, tradisi lama dari Agama Bali masih menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Baru pada bagian kedua dari milenium pertama pengaruh India mulai masuk, pertama dalam ajaran Buddha, kemudian setelah Majapahit, dalam bentuk Hindu-Buddha, Siwaisme.
Perubahan ini semakin cepat karena menyertai urbanisasi masyarakat yang cepat, yang sangat melemahkan dukungan sosiologis lama dari agama Bali. Banyak sekte dan asosiasi India masuk untuk tujuan kesadaran spiritual . Dewa-dewa India mendapatkan kedudukan lebih tinggi, sementara para dewa lokal kembali ke batu, pohon, dan gunung-gunung lain dari asal mereka.
Artikel kali ini berfokus pada ritual yang terkait dengan pemujaan leluhur terhadap upacara “Kematian” yang untuk selanjutnya dilakukan upacara pengabenan. Karena perbedaan yang paling mencolok antara kedua kutub, masing-masing India dan Nusantara (Bali), adalah dalam perawatan dan interpretasi kematian.
Pemujaan leluhur Hindu Bali
Lalu bagaimana, tepatnya, tentang kematian dan perawatannya?
Untuk mendekati pertanyaan ini, perlu ada gagasan tentang apa yang secara konkrit disembah leluhur di Bali, sebagaimana terus berlanjut di balik layar formal agama Hindu dewasa ini. Dalam akal sehat orang Bali, bahwa dari kaum tani pedalaman, di atas pegunungan adalah apa yang dikenal sebagai “negara lama” ( tanah sane wayah ), tempat tinggal para jiwa leluhur yang telah dimurnikan menjadi “air” (suba dadi yeh).
Selama perayaan hari besar seperti Galungan dan Kuningan (Belo 1953; Darta, Couteau, Breguet 2013), jiwa-jiwa ini, yang dikenal dan tidak dikenal, disertai oleh sekelompok dewa ( dewa-dewi ) dan dewa-dewa bawahan lainnya ( rencang , ancangan ) turun (tedun ) dalam bentuk tidak berwujud mengunjungi mereka yang mereka sebut “anak kecil” ( cening ). Mereka kemudian tinggal di patung ( pratima ), dimurnikan untuk tujuan ini, yang dikaitkan dengan mereka di altar berbagai keluarga dan kuil klan.
Kami memperlakukan mereka seperti hidup: kami memandikan mereka di sungai ( mesucian ), berpakaian mereka, berjalan mereka di tempat-tempat dan kuil-kuil memori desa, menawarkan mereka tarian ( pendet ) dan makanan ( ayaban) selama kunjungan mereka, sebelum mengirim mereka kembali ke tempat tinggal leluhur mereka. Perhatian yang dicurahkan sangat ekstrem. Untuk almarhum terbaru, orang-orang yang ingatannya kita miliki, kami menawarkan makanan favorit mereka. Untuk yang tertua, mungkin ada pertunjukan tari topeng ( pajegan ) di mana sejarah klan diputar ulang, di mana mereka dikatakan protagonis. Beberapa dari roh leluhur ini dapat mengambil sesaat roh dari salah satu keturunan mereka, menjadi wadah ( tapakan ): itu adalah trans.
Tarian sederhana, atau sarana bagi leluhur untuk merumuskan permintaan khusus: pembangunan altar, permintaan ziarah, dll. Mereka juga dapat dilihat melalui balian/ sedang, untuk mengetahui kesalahan apa yang akan dilakukan oleh ini atau kesalahan “kecil” mereka, ketidakmurnian apa yang akan ditimbulkannya. Di luar perayaan, komunikasi tetap berlanjut setiap hari melalui persembahan (saiban) dan doa-doa ditujukan secara informal, setiap hari, kepada “kakek” (khaki), “nenek” (nini), di altar asal-usul (kemulaan / kawitan), terletak di kuil keluarga (sanggah / merajan) di pusat garis silsilah altar timur ( kangin ) dari candi tersebut.
Karena itu kita dapat melihatnya dengan jelas, jika Hinduisme, baik Hindu-Buddha dan sekarang Neo-Hindu, adalah wacana pemujaan leluhur adalah fondasinya.
Sinkretisme
Jiwa leluhur orang Bali tetap diambil di jalur yang berulang. Dia kembali ke bumi. Di sinilah tanda keagamaan, seperti yang dijelaskan secara singkat di atas, terjalin dengan tanda terkuat dari pengaruh pemikiran Hindu di India: gagasan Hindu tentang samsara, rantai inkarnasi dari jiwa dipegang oleh nafsu (rajas).
Orang Bali mengatakan bahwa jiwa leluhur turun dan mencari untuk kembali ke bumi untuk “meminta Beras” ( nunas Baas ) atau “permintaan untuk berbicara” (nunas pawisik). Ini adalah reinkarnasi, yang disebut sebagai “tetesan” (titisan) yang jatuh dari ketinggian pegunungan, merujuk pada peran gunung sebagai asal, baik leluhur maupun perairan, sebelum pengaruh India. Dari langit, jiwa yang diwujudkan melanjutkan perjalanan hidup sampai kembali ke asalnya.
Mari kita melihat tahapan perjalanannya, di mana pemujaan leluhur dari tradisi pribumi dan peminjaman Hindu-Budha bergabung.
Jiwa, yang juga dikatakan keluar dari api penyucian Hindu, tidak berinkarnasi dengan cara apa pun. Ini bergantung pada tindakan seksual, dan tidak turun secara kebetulan untuk mencampuri yang terakhir, kecuali kekerasan atau penyimpangan lainnya. Idealnya, itu terjadi setelah doa yang dirumuskan oleh pasangan di kuil atau pura leluhur klan mereka, di mana leluhur berada lebih jauh daripada keluarga dekat. Dikatakan tentang pasangan yang menyatukan bahwa itu dianimasikan oleh dewa lirikan (Sanghyang Deleng), dan bahwa ia menyadari pada tingkat daratan persatuan kosmik dewa cinta, Kamajaya, dan dewi bulan Ratih. Persatuan mereka juga dengan keinginan merah (kama bang) dan keinginan putih (kama petak), lambang sel telur dan sperma masing-masing. Ini membuka pintu menuju turunnya jiwa leluhur yang menunggu inkarnasi.
Karena di Bali, seseorang turun dari “negara lama” untuk menjelma di antara miliknya sendiri (numadi), oleh karena itu di antara orang-orang dari klannya dan “kasta” -nya, dan tidak diberi status yang ditentukan oleh kualitas dari tindakan masa lalu karmapala sesuai dengan konsepsi Hindu normatif.
Ritus-ritus yang diikuti selama kehidupan melanjutkan perpaduan dua tradisi, agak asli untuk ritus kelahiran, dan semakin diwarnai dengan agama Hindu India seiring terbukanya dan bertambahnya usia untuk nafsu (rajas). Namun, menurut sebagian besar orang Bali, pada akhir kehidupan dan oleh karena inkarnasi yang sedang berlangsung, jiwa mendapatkan kembali status asalnya sebagai leluhur yang didewakan yang berada di atas gunung.
Ritus pertama yang ditujukan kepada orang yang diwujudkan terdiri dari jabang bayi di dalam rahim wanita, yaitu megedong-gedongan. Dia memiliki status dewa kecil, yang akan disimpan anak di masa kecilnya, sebuah tanda kehadiran nenek moyang yang didewakan. Setelah lahir, serangkaian upacara dihubungkan mirip dengan yang ditemukan di populasi lain di kepulauan ini, dan yang menegaskan keberadaan dewa berwujud di bumi : penguburan “empat saudara kecil” (catur sanak); upacara hari kelima atau ketujuh untuk memotong tali pusat (kepus pungsed); upacara hari kedua belas untuk mengidentifikasi leluhur menggunakan media; hari keempat puluh dua untuk langkah pertama; bahwa bulan ketiga, yang menandai masuknya ke dalam kalender Jawa-Bali 210 hari ( Pawukon ). Tujuan ritus-ritus pertama ini adalah untuk menyambut dan membimbing masuknya anak ke dalam kehidupan.
Ritus yang paling penting adalah ritus hari kedua belas, ketika orang tuanya berusaha menemukan asal-usulnya, yaitu, bertanya tentang leluhur mana yang telah mengambil bentuk wujud dan permintaan apa yang harus dia buat. Mereka berkonsultasi untuk tujuan ini pada orang pintar (balian), yang dapat memanggil jiwa yang lahir (Numadi). Mereka menanyakan namanya, asal usulnya pada generasi yang lalu, misalnya: “siapa yang datang ke sini meminta beras” (nyen ane ngidih nasi)? “Saya adalah kakekmu dari sebelah barat sungai” (tiang kakiangmu uli dauh tukad). Dia juga ditanya apakah dia memiliki satu atau lebih permintaan khusus untuk dipenuhi, untuk menjaga kesehatan dan kemakmuran bayi yang baru lahir. Keluarga berusaha untuk memenuhi permintaan ini, yang sangat bervariasi: itu bisa berupa pemeberian seperti seperangkat kain atau pakaian (rantasan) untuk diberikan kepada anak itu.
Adalah perlu untuk mengasumsikan secara seimbang dikatakan tiga tujuan umat Hindu di kehidupan ini: keinginan (kama), kekayaan (artha) dan kebajikan (dharma). Usia muda (brahmacari) adalah kendali kendali hasrat, yang secara simbolis ditekan dalam upacara potong gigi (metatah), menginjak dewasa (grehasta) adalah latihan hasrat, hubungan dan akumulasinya dengan pernikahan sebagai ritual utama; usia lanjut (wanaprasta) adalah dharma yang dimahkotai oleh imamat. Tujuan tertinggi, di luar kehidupan, tetap menuju moksha.
Kematian
Dalam ritus kematian, pemujaan leluhur muncul kembali dengan cara kremasi. Tujuannya adalah membebaskan jiwa orang mati dan membiarkannya kembali ke asalnya, di atas gunung. Setelah kematian, jiwa memang tanpa “tinggal” stabil; ia tidak lagi ada di dalam tubuh, juga tidak dibebaskan dari ikatan duniawinya. Dia mengembara dengan cara yang berpotensi berbahaya di sekitar orang mati; oleh karena itu seorang harus menetralkannya, menyediakannya dengan tempat tinggal sementara, tergantung pada saat “perjalanan” kembali ke asal-usulnya, yang merupakan subjek dari sejumlah persembahan dan ritus, disertai dengan dialog singkat antara dia dan orang-orang yang dicintainya.
Kemudian melakukan penguburan sementara untuk beberapa bulan atau tahun dengan cara di atas api (mekingsan di geni), atau di tanah (mekingsan di pertiwi) dengan penguburan (metanem). Perawatan Jiwa dipercayakan pada dewi kematian, Durga.
Langkah-langkah ini adalah untuk prosedur pemisahan antara jiwa dan tubuh, sambil menunggu dapat melakukan kremasi lengkap (Ngaben). Dalam kasus penguburan sementara (mekingsan di pertiwi) terjadi upacara penggalian orang mati (ngagah).
Ritual krematorium dan pasca krematorium mengatur pemisahan secara bertahap elemen-elemen berwujud dari tubuh dan tidak berwujud (jiwa) dari almarhum: sisa-sisa tubuh yang sudah dihaluskan akan berakhir di laut, dan jiwa akan bergabung dengan ” negara lama ” dari luar pegunungan. Perangkat simbolik yang digunakan pada dasarnya adalah Hindu-Buddha. Mereka terlebih dahulu mengangkut tubuh dari pemakaman (setra). “Wadah / Bade” tempat untuk peti mayat (Catafalque) digunakan untuk tujuan ini, di mana ada beberapa jenis tergantung pada kelompok klan dan kemampuan keluarga. Dalam keluarga yang paling sederhana, ini terdiri dari sebuah kotak peti mati sederhana (wadah) yang juga akan digunakan untuk kremasi yang sebenarnya. Di keluarga lain, wadah itu terletak di bagian tengah menara bade atau crematory, yang mewakili Tripartisi Hindu, dengan simbol chtonian (kura-kura, naga dan Bhoma) di bagian bawahnya, simbol Uranian (level / loka). langit, hingga sebelas di bagian atasnya, dan tubuh patung (pengawak) almarhum atau pengganti dipasang di bagian tengahnya, yang mewakili dunia tengah, selanjutnya diangkut ke kuburan untuk kremasi.
Tiba di kuburan, sebelum dibakar, mayat itu dipindahkan ke sarkofagus (petulangan), beberapa di antaranya sangat sederhana, yang lain dengan dekorasi dalam bentuk sapi, singa, harimau, dll., sesuai klan.
Pada bagian akhir Kremasi dilakukan penyebaran unsur-unsur tubuh yang telah dihaluskan ke sungai, kemudian ke laut. Perlu dicatat bahwa penyebaran tubuh berjalan ke hilir (ngelodang), simbolisasinya juga guna melewati dari bagian bawah, ke bagian hilir desa dan menyebar di bagian bawah pulau.
Sekarang tergantung pada jiwa untuk membebaskan dirinya untuk jalannya kembali ke hulu (ngajanang), menuju ketinggian pegunungan dan “negara tua” dari arwah leluhur yang akan meningkatkan statusnya menjadi dewa ( dewa pitara, dewa hyang ).
Fase-fase berikut: kita mengingat jiwa yang tersebar dilautan murni, dipercayakan padanya dan kita mengirimkannya ke ketinggian asal-usulnya: itu adalah dengan upacara nyegara-gunung, biasanya dilakukan di Goa Lawah, di kaki bukit di tepi laut.
Jiwa yang dimurnikan sejak saat itu, dewa pitara atau dewa hyang, kemudian diberitahukan (mapejati), dengan rangkaian persembahan dilakukan meajar-ajar guna membawa Jiwa leluhur kembali ke tempat atau kuil klan keluarganya.
Kemudian upacara terakhir menstanakan leluhur (ngelinggihang), dilakukan di kemulan / kawitan kuil keluarga, dan akan menjadi titik acuan untuk pemujaan leluhur.