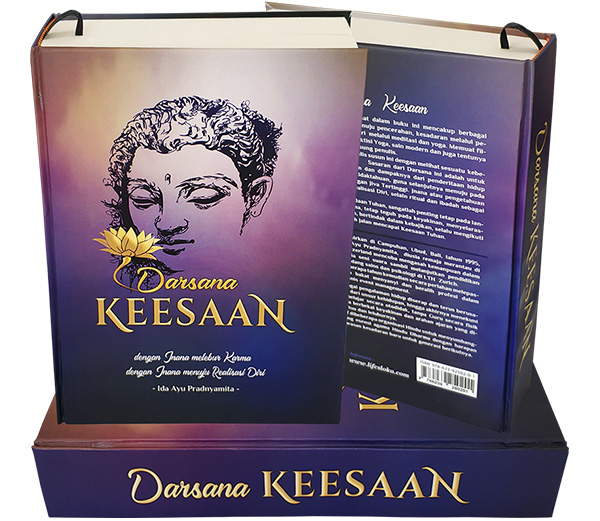Agama leluhur adalah istilah yang baru populer sejak era Reformasi. Agama leluhur sering digunakan secara bergantian dengan “agama asli,” “agama lokal,” “agama nusantara,” dan bahkan sering diidentikkan dengan “kearifan lokal.” Tulisan ini tidak berkepentingan untuk merumuskan definisi agama leluhur dan istilah-istilah serupa lainnya. Yang dipentingkan adalah kejelasan subjek materi dari penggunaan istilah tersebut. Agama leluhur merujuk pada praktik-praktik keagamaan lokal (subjek materi) yang sering diklaim sebagai praktik animis, magis, adat, budaya dan seterusnya, baik dalam wacana publik maupun dalam literatur (Maarif, 2016, 2017). Di antara contoh praktiknya adalah semedi, sesajen, kunjungan (ritual) ke gunung, hutan, sungai, dan lain-lain, bersih desaan seterusnya.
Sebagaimana agama-agama lain, yang dalam studi agama disebut sebagai “agama dunia,” agama leluhur juga memiliki penganut. Penganutnya tersebar di berbagai daerah di nusantara. Jumlah mereka yang diidentifikasi dan meregistrasi diri di lembaga-lembaga negara, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kejaksaan melalui Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), berubah dari waktu ke waktu, dari 200 hingga lebih 300 kelompok/organisasi. Terakhir, menurut catatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, jumlah mereka yang teregistrasi adalah 182 organisasi di tingkat pusat, dan lebih 1.000 organisasi di tingkat cabang (daerah).
Penganut agama leluhur terdiri dari penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Tidak semua penghayat dan masyarakat adat -karena banyak di antara mereka menolak- disebut sebagai penganut agama leluhur, dengan berbagai pertimbangan. Praktik adat/kepercayaan mereka misalnya disebutnya sebagai budaya bukan agama. Seperti akan dijelaskan dalam pembahasan, kategori agama dan budaya harus dipahami dalam konteks politik agama, di mana keduanya merupakan konstruksi politik, tepatnya bahasa kebijakan, untuk menentukan siapa yang (tidak) boleh diakui, dilindungi dan dilayani oleh negara. Terdapat enam kelompok yang akhirnya diakui, dilindungi dan dilayani sebagai kelompok penganut agama. Selain itu, khususnya penganut agama leluhur dikategorikan sebagai budaya dan karenanya tidak mendapatkan pelayanan dari negara atas nama pelayanan agama. Sekalipun kebijakan tersebut baru efektif sejak tahun 1978, tidak sejak Indonesia merdeka, tetapi dampaknya sangat hegemonik, seakan ahistoris.
Sebagai istilah, agama leluhur memang baru, tetapi subjek materinya telah eksis sebelum Indonesia merdeka. Narasi-narasi eksistensi agama leluhur bahkan menjangkau masa waktu yang tidak tercatat oleh sejarah, atau catatan sejarahnya menggunakan label lain, seperti primitif, animis, magis dan berbagai istilah pejoratif lainnya. Ia telah hadir sejak dulu bahkan sebelum dikenal istilah agama. Dalam konteks ini, agama leluhur secara politis dipahami sebagai kategori yang dibedakan dari agama resmi negara. Agama resmi negara: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sering dinarasikan sebagai “agama impor,” dan agama leluhur adalah agama asli nusantara. Dalam perkembangannya, agama impor dijadikan sebagai agama resmi negara, sementara agama asli nusantara justru didiskreditkan, didiskriminasi dan dikriminalisasi. Ia justru dihancurkan dengan berbagai alasan seperti kemajuan, modernitas, pembangunan, dan seterusnya.
Pembedaan agama leluhur dari agama resmi negara tidak harus dipahami bahwa keduanya senantiasa saling bertentangan (mutually exclusive), setelah memeluk Islam, Kristen, Hindu, dan lainnya, seorang pemeluk agama leluhur otomatis meninggalkan agama leluhurnya, sebagaimana kecenderungan dominan dalam wacana publik, dan bahkan pengajaran/studi agama hingga hari ini (agama dipahami dan diajarkan secara eksklusif seakan bertentangan sama sekali dengan yang lainnya). Dalam realitasnya, segera setelah agama resmi dan agama leluhur bertemu dan berinteraksi, keduanya saling mempengaruhi dan saling berbagi, dan juga saling menundukkan. Banyak yang telah memeluk Islam, Kristen atau Hindu misalnya, tetapi mereka tidak meninggalkan adat/kepercayaan atau agama leluhurnya. Islam Kejawen, Islam Aboge, Islam Ammatoa, Hindu Kaharingan, Kristen Dayak, dan masih banyak lagi yang lainnya adalah contoh dari dampak pertemuan dan interaksi antara agama resmi negara dan agama leluhur. Sebagian menteorikan fenomena tersebut sebagai bentuk sinkretisme, tetapi jika merujuk pada persepsi penganut agama leluhur, agama dan adat/kepercayaan lokal tidak harus dipertentangkan. Keduanya jika mengandung ajaran kebaikan dan kebenaran dapat saja diterima, diikuti dan dipraktikkan. Memeluk Islam atau Kristen tidak meniscayakan hilangnya adat/kepercayaan lokal atau agama leluhur.
Persepsi lain, agama resmi negara dipeluk karena dipaksa. Bertahan pada agama leluhur berakibat fatal, mengancam keselamatan. Menjadi Islam, Kristen atau Hindu adalah untuk bertahan hidup. Persepsi penganut agama sangat beragam. Semuanya ditentukan oleh pengalaman masing-masing. Namun poin yang ingin ditunjukkan di sini adalah agama leluhur tidak harus dipertentangkan dengan agama resmi dalam pengertian bahwa jika seorang memeluk agama resmi, ia akan kehilangan agama leluhurnya. Agama leluhur tetap dipertahankan, bahkan dijadikan rujukan otoritas utama untuk religiusitasnya, sekalipun sudah mengidentifikasi diri sebagai pemeluk agama resmi, seperti Islam atau Kristen, dan lain-lain.