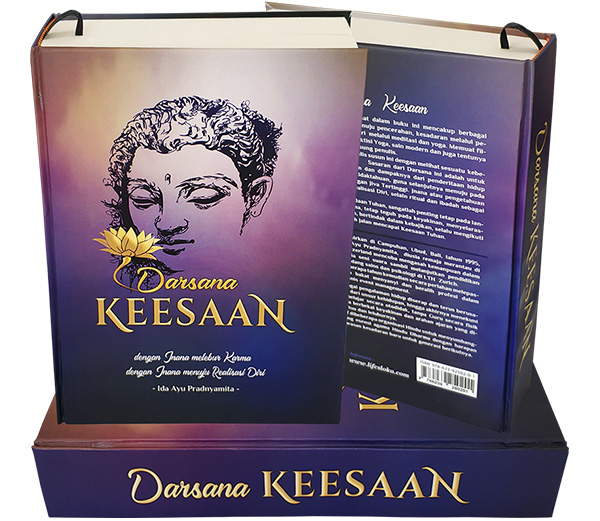Legalisasi Kesetaraan Agama Leluhur
Setelah kekuasaan beralih ke Suharto pada tahun 1968, Suharto mulai menancapkan fondasi rezim Orde Baru. Partai politik Sukarnois, Partai Nasional Indoensia (PNI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan partai-partai politik, termasuk partai-partai Islam dipaksa untuk melebur ke salah satu dari dua partai: Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Rabasa and Haseman, 2002: 36; dikutip dari Noer, 2000). Di sisi lain, penguasa membentuk Golongan Karya (Golkar) sebagai instrumen politik rezim Orde Baru-nya.
Di bawah SKK Golkar, kelompok kebatinan diminta untuk mengganti nama “kebatinan” menjadi “kepercayaan.” Seperti terlihat sebelumnya, keduanya, “kebatinan” dan “kepercayaan”, sebenarnya digunakan secara bergantian. Di bawah Golkar, “kepercayaan” diminta untuk lebih dipopulerkan. Pertimbangannya adalah untuk menegaskan status hukum (konstitusional) kelompok tersebut. Penggunaan kepercayaan bagi kelompok tersebut dapat dikaitkan langsung dengan UUD 1945 Pasal 29. Sekali lagi, sejak di bawah SKK Golkar, aliran kebatinan berubah menjadi aliran kepercayaan, dan organisasi kepercayaan secara resmi menjadi bagian dari Golkar (Patty, 1986:11).
Di bawah Golkar, kelompok kebatinan terus berusaha menghimpun seluruh penganut kepercayaan dalam satu wadah organisasi yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan secara legal dari negara. Pada masa ini pula, kelompok masyarakat adat yang tersebar di luar Jawa diikutsertakan. Tradisi-tradisi adat –yang pada masa penjajahan Belanda dilabeli sebagai animis tetapi pada waktu yang sama direvitalisasi, pada masa penjajahan Jepang dipinggirkan karena dianggap antek penjajah Belanda dan bertentangan dengan Islam, dan setelahnya kajian adat lebih diidentikkan dengan hukum (hukum adat)– dikategorikan sebagai kepercayaan, kerohanian dan kebatinan. Pada tanggal 7-9 November 1970, BK5I mengadakan simposium. Prof. Pringgodigdo, salah satu perumus UUD 1945, menjelaskan di simposium tersebut bahwa pengertian “kepercayaan” pada Pasal 29 adalah kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian. Selain itu, kedudukan kepercayaan adalah sejajar dengan agama (Dwiyanto, 2010: 287).
Pada bulan berikutnya, tepatnya pada 27-30 Desember 1970, mereka melaksanakan Musyawarah Nasional Kepercayaan di Yogyakarta. Dalam musyawarah tersebut, mereka menegaskan bahwa salah tafsir terhadap Pasal 29 UUD 1945 telah merugikan aliran kepercayaan. Kata “kepercayaan” pada pasal tersebut seharusnya dipahami dan diakui sejajar dengan agama. Aliran kepercayaan berhak mendapatkan perlakuan setara di hadapan hukum, hak organisasi, pengajaran kebatinan di sekolah, hak perkawinan khusus, dan subsidi dari pemerintah. Mereka menjelaskan bahwa kata “kejiwaan” (dari jiwa) dan “kerohanian” (roh) muncul setelah “kebatinan.” Semua kata-kata tersebut dirangkum menjadi kepercayaan (dikutip dari Subagya, 1981). Uraian konsep-konsep tersebut didasarkan pada mistisisme Jawa atau kejawen (sering dikonotasikan dengan takhayul, magis, dan klenik atau occultism). Konsep-konsep tersebut semuanya menekankan makna keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aliran kepercayaan juga memiliki rangkaian doktrin dan struktur jamaat/umat, sehingga kedudukannya tak perlu diragukan setara dengan agama (Patty, 1986:10; Dwiyanto, 2010: 287).
Keputusan pemerintah, melalui Golkar, yang menerima organisasi kepercayaan sebagai lembaga formal adalah sebuah langkah penting karena dengan demikian pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan melayani kelompok tersebut secara finansial, sebagaimana kelima kelompok agama (Patty, 1986:11). Pada 20 Januari 1971, delegasi Munas Kepercayaan yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro menghadap Presiden Suharto. Mereka mengajukan empat hal: 1) legalitas kehidupan kepercayaan (kebatinan, kerohanian, kejiwaan), 2) pendidikan moral Pancasila, 3) kedudukan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan, dan 4) perayaan Satu Syuro sebagai hari besar Kepercayaan. Sebagai tindak lanjut, pada 27 Januari 1971 “Satu Syuro Syaka 1901” dirayakan di berbagai tempat, dengan doa, sesaji, pewayangan, serta sambutan-sambutan, termasuk sambutan yang dibawakan langsung oleh Presiden Suharto (Dwiyanto, 2010: 288).
Pada tanggal 5-12 Agustus 1971, Kongres Internasional Subud (salah satu kelompok kepercayaan terbesar, yang pesertanya terdiri dari perwakilan 79 negara) diadakan di Jakarta, dan dihadiri oleh Presiden Suharto. Sang presiden bahkan memberi sambutan yang menegaskan, “Pemerintah harus memberikan tempat yang wajar kepada aliran kepercayaan, kerohanian, kejiwaan, dan kebatinan (Dwiyanto, 2010: 288).” Posisi politik dan dukungan pemerintah terhadap kelompok kepercayaan semakin meningkat setelah pemilu 1971. Sekretariat Kerja Sama antar-Kepercayaan-Kebatinan, Kejiwaan dan Kerohanian (SKK) terus berusaha untuk mensistematisasi dan memformalkan ajaran-ajaran kepercayaan dengan tujuan untuk memenuhi “persyaratan” pengakuan, dan perwakilan secara resmi dalam Direktorat Jenderal di Kementerian Agama. Lebih lanjut, pada tanggal 16 Februari 1972, dalam perayaan Satu Syuro di Istora, Menteri Agama Mukti Ali mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang aliran-aliran kepercayaan (Dwiyanto, 2010: 288).
Upaya pemerintah untuk mensetarakan kepercayaan dengan agama tentu saja mendapat protes, seperti sebelumnya. Pada tanggal 11 April 1972, Lembaga PAKEM yang telah direorganisasi dan juga didirikan di berbagai daerah melaporkan bahwa terdapat 427 Cabang Kebatinan, 217 aliran kepercayaan, dan sebanyak 188 dari aliran-aliran tersebut berada di Jawa Tengah. Semua aliran yang berjumlah 644 tersebut terdaftar di Sekretariat Kerjasama Kepercayaan, pada tingkat pusat dan cabang. (Dwiyanto, 2010: 87). Pada bulan yang sama, tokoh Islam, Hamka menerbitkan brosur-brosur yang bertema “Mengembalikan kebatinan kepada pangkalnya.” Brosur tersebut adalah bentuk kampanye untuk membendung gerakan aliran-aliran kepercayaan yang menuntut pengakuan setara dengan agama. Akan tetapi, gerakan kelompok Islam untuk mengembalikan aliran-aliran kepercayaan yang diklaim sejatinya “berinduk” kepada agama tidak berhasil (Dwiyanto, 2010: 288).
Menjelang Sidang MPR 1973, upaya legalisasi kesetaraan kepercayaan semakin menguat, dan perkembangan tersebut juga semakin memancing reaksi protes dari kelompok Islam. Pers Islam meningkatkan kampanye “hitam” terhadap kelompok kepercayaan sebagai klenik, keberhalaan, dan takhayul (Dwiyanto, 2010: 288). Terlepas dari kampanye tersebut, secara de facto posisi kepercayaan diakui setara dengan agama sebagaimana tercantum dalam GBHN yang disusun dan diputuskan melalui TAP MPR 1973 (Moulder, 1978: 8). TAP MPR 1973 dengan demikian adalah bukti bahwa tuntutan kelompok kepercayaan untuk diakui setara dengan agama diterima oleh negara. TAP MPR 1973 sebagaimana tercantum dalam GBHN misalnya menegaskan bahwa kepercayaan dan agama adalah ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan YME yang sama-sama sah (dikutip dari Subagya, 1976: 125).