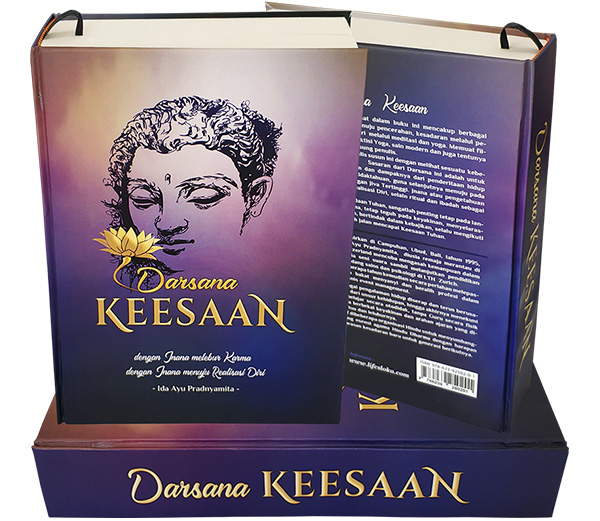Keragaman Persepsi Agama vs Adat
Di level masyarakat, “agama” dan “adat” di satu sisi sering dipertentangkan, tetapi di sisi lain, keduanya juga kadang dianggap sama, atau paling tidak keduanya tidak bertentangan. Komunitas agama yang memiliki orientasi agama modern, ortodoks, dan puritan umumnya menganggap adat sebagai unsur budaya yang mencemari agama, tetapi komunitas agama yang memiliki orientasi keagamaan tradisional-kontekstual cenderung menerima adat sebagai sumber pengayaan agama. Selama adat tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama, misalnya ajaran tentang keesaan Tuhan, adat dapat dianggap sebagai unsur yang memperkaya keberagamaan.
Keragaman persepsi terkait makna agama vs. adat seperti di atas lazim pada masa penjajahan Belanda sampai ketika pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan pembedaan Agama vs adat di akhir abad ke-19. Akibat dari kebijakan tersebut, adat yang dilembagakan menjadi eksklusif berbeda dari institusi agama, dan kelompok agama pada gilirannya menganggap bukan hanya penjajah Belanda tetapi juga kelompok adat sebagai musuh, karena dianggap beraliansi dengan penjajah. Model kebijakan ini sering disebut sebagai “politik belah bambu”: warga negara dibelah dan dibedakan. Kelompok pertama ditekan, dan lainnya dikuatkan. Kebijakan pembedaan tersebut berdampak pada polarisasi dan ketegangan sosial antara kelompok Agama vs. kelompok adat.
Terkait dengan kebijakan pembedaan di atas, pemerintah Belanda pada masa yang sama juga mengeluarkan kebijakan “politik etis” yang menekankan kewajiban bagi pemerintah penjajah untuk memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat jajahan. Dalam konteks kedua kebijakan tersebut, pemerintah penjajah cukup dilematis karena di satu sisi adat yang dilembagakan dan dikuatkan dipahami sebagai budaya “animis” (bukan agama, atau psudo-agama), anti-Eropa, dan antikemajuan.
Adat yang menurut Subagya adalah agama asli atau agama leluhur Indonesia dianggap primitif dan animis (Kruyt, 1915). Mereka perlu dimodernkan. Adat, sebagai agama leluhur, diakui eksistensinya, didukung keberlanjutannya, tetapi perlu diubah menjadi kemajuan, disesuaikan dengan kultur Eropa. Adat yang direvitalisasi direduksi maknanya. Status keagamaannya dianggap animis (psudo-agama) sebagaimana yang berkembang di Barat (Fitzgerald, 2003, 2007).
Masih terkait dengan konteks kebijakan politik etis pemerintah Belanda, tuntutan terhadap pluralisme hukum juga berkembang. Pemerintah dituntut tidak hanya menjalankan sistem hukum berdasarkan hukum Barat/Eropa. Ia juga dituntut untuk mengakui sistem hukum yang hidup dalam masyarakat jajahan. Penelitian hukum adat (adatrecht) kemudian dikembangkan oleh Van Vallenhoven, murid C. S. Hurgronje. Praktik-praktik adat di nusantara yang diidentifikasi memiliki konsekuensi hukum didokumentasikan (Fasseur, 2007).
Kajian adat berkembang, bahkan hingga saat ini, melalui pengembangan studi hukum adat. Makna adat yang sebenarnya sangat luas, mencakup berbagai dimensi kehidupan komunitas, tereduksi menjadi identik dengan hukum. Adat adalah tentang hukum. Masyarakat adat dipahami sebagai masyarakat hukum adat. Identifikasi adat sebagai hukum (semata) tentu berdampak pada eliminasi adat sebagai agama (Maarif, 2012).