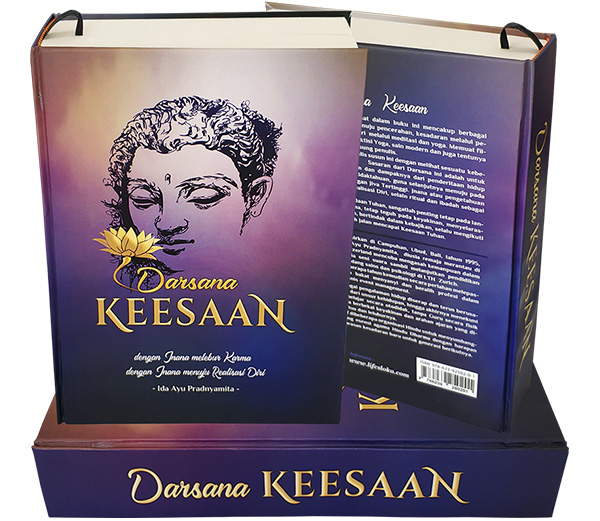Upaya Menyetarakan Kebatinan dengan Agama
Ketika Depag berhasil membedakan kepercayaan (bukan agama) dari agama, Depag seakan semakin “sah” menekan “lawannya.” Di pihak lain, kelompok yang belakangan menyebut diri sebagai kelompok kebatinan mengkonsolidasikan diri. Mereka mendirikan berbagai perkumpulan dan organisasi. Pada tanggal 20 Mei 1949 Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) dibentuk, dan setelah itu menyusul seperti Islam Sejati, Mistik Jawa-Hindu, Kawruh Naluri, Agama Merah Budha Budhi, dan lain-lainnya (Dwiyanto, 2010: 284). Pada Tahun 1951, Panitia Penyelenggara Pertemuan Filsafat dan Kebatinan yang dipimpin oleh Mr. Wongsonegoro mengadakan pertemuan bulanan. Kelompok ini kemudian melebur dalam Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) yang belakangan dibentuk. Singkatnya, pada awal tahun 1950-an, berbagai kelompok kebatinan bermunculan. Pada tahun 1952, Depag Jawa Barat melaporkan kemunculan 29 aliran kepercayaan (Kroef, 1961: 18). Selanjutnya pada tahun 1953, Depag kembali melaporkan perkembangan aliran kepercayaan yang sudah mencapai 360-an (Subagya, 1981; Sihombing, 25-26).
Perkembangan kelompok kebatinan yang sebelumnya diklaim sebagai kelompok yang tidak/belum beragama tentu saja menyita perhatian pihak Depag. Di pertengahan tahun 1956, Depag kembali mengumumkan bahwa terdapat 63 aliran kebatinan di Jawa yang bukan pemeluk agama Islam, Protestan, dan Katolik: 35 berada di Jawa Tengah, 22 di Jawa Barat, dan 6 di Jawa Timur (Kroef, 1961: 18). Bagi Depag, fakta tersebut menunjukkan bahwa ancaman kelompok kebatinan telah menjadi kenyataan. Lebih lanjut, pada tanggal 17-19 Agustus 1956, Kongres II dilaksanakan di Solo. Pada kongres ini, hadir sekitar 2000 perwakilan dari 2 juta anggota kebatinan di seluruh Indonesia (Patty, 1986: 2; dikutip dari Mulder, 1978:5). Pada kongres tersebut, mereka memformulasikan definisi kebatinan sebagai prinsip dan sumber azas sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mencapai budi luhur, dan guna kesempurnaan hidup. Merespons tekanan Depag, kelompok kebatinan juga mendeklarasikan bahwa kebatinan bukan, dan tidak untuk menjadi agama baru, tetapi untuk meningkatkan kualitas keagamaan (Subagya, 1981: 76; Patty, 1986: 70; Dwiyanto, 2010: 285). Mereka seakan tanpa pilihan kecuali tunduk pada tekanan Depag bahwa agama harus memenuhi kriteria sebagaimana yang didefinisikannya. Akan tetapi, pada tahun 1957 BKKI mencoba melepaskan diri dari tekanan Depag. Mereka bersurat dan meminta Presiden Sukarno untuk mengakui status kebatinan setara dengan agama, dan mengusulkan 5 perwakilan mereka sebagai anggota Dewan Nasional (Patty, 1986: 70).
Namun pada masa itu pula, Pemuda Islam Indonesia, melalui kongresnya yang keempat, mengeluarkan resolusi meminta pemerintah untuk melarang berbagai bentuk klenik (Dwiyanto, 2010: 285). Istilah klenik ini adalah stigma negatif yang umum dilabelkan kepada praktik kebatinan pada waktu itu. Respons Sukarno kemudian disampaikan pada Kongres III BKKI pada 17-20 Juli 1957. Di kongres itu, Presiden Sukarno memberi sambutan penghargaan kepada kelompok kebatinan karena menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah organisasi dan kehidupan mereka. Namun, pada saat itu juga, Presiden Sukarno, dalam sambutannya, mengingatkan untuk berhati-hati dengan klenik atau ilmu hitam. Kongres tersebut pun menegaskan bahwa kebatinan bukan klenik, tetapi merupakan aktivitas spiritual murni (atau bisa disebut “ilmu putih”) (Patty, 1986: 70-71), sebuah upaya pencarian keharmonisan dalam diri, antara diri dan sesama manusia, dengan alam, dan dengan Tuhan Yang Maha Esa (Patty, 1986: 3-4; dikutip dari Lee, 1976).
Dua tahun setelah kongres di atas, tepatnya pada tanggal 14-15 November 1959, BKKI mengadakan seminar di Jakarta. Seminar tersebut mendiskusikan tentang pendidikan nasional dan merekomendasikan agar kebatinan menjadi prinsip Pergulatan wacana agama vs. kebatinan di atas direkam dalam rumusan TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 yang ditetapkan di kota Bandung pada tanggal 3 Desember 1960.
Pada Pasal 2, Bidang Mental/Agama/Kerohanian/Penelitian ayat (1) menyatakan:
(1) “Melaksanakan Manifesto Politik di lapangan pembinaan Mental/Agama/Kerohanian dan Kebudaya-an dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing.”
Frase “Mental/Agama/Kerohanian dan Kebudayaan” yang dituliskan pada ayat (1) di atas menunjukkan bahwa “denominator” kebatinan: “kerohanian” dan “kebudayaan” diakomodasi setara dengan “agama.” Pergerakan kelompok kebatinan cukup efektif mempersoalkan definisi agama yang digunakan Depag. Mereka berhasil mendapatkan pengakuan secara setara. Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak berarti bahwa tekanan terhadap mereka selesai. Pada pasal yang sama yaitu Pasal 2 ayat (3) misalnya menyatakan:
“Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.”
“Pendidikan agama” pada ayat (3) di atas di satu sisi menunjukkan tekanan kelompok santri terhadap kelompok kebatinan, di mana anak-anak mereka akan mendapatkan pendidikan agama (bukan kebatinan) yang mereka tidak yakini. Tetapi di sisi lain, terjaminnya hak untuk tidak mengikuti pelajaran agama menunjukkan posisi tawar kelompok kebatinan (Suhadi, 2014).
Berkaitan dengan itu, pada 28-29 Januari 1961, Kongres Nasional BKKI dilaksanakan di Ponorogo, Jawa Timur. Pada kongres ini, mereka mengeluarkan beberapa pernyataan: (1) prinsip kebatinan adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe; Memayu-hayuning bawana; (2) pendidikan moral bagi pembangunan karakter harus diajarkan di setiap level pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi; dan (3) Ketuhanan harus melandasi pikiran dan praktik kehidupan sehari-hari (Patty, 1986: 71-72). Poin kedua jelas merupakan respons terhadap ayat (3) Pasal 2 sebelumnya. Pendidikan moral adalah alternatif dari pendidikan agama. Sebagai bagian dari respons terhadap tekanan melalui pendidikan agama di sekolah-sekolah, pada bulan April 1961, kelompok kebatinan membentuk Gabungan Musyawarah Kebatinan Indonesia (GMKI). Tujuan GMKI adalah memberi perhatian lebih pada masalah pendidikan, informasi dan politik (Patty, 1986: 71-72).