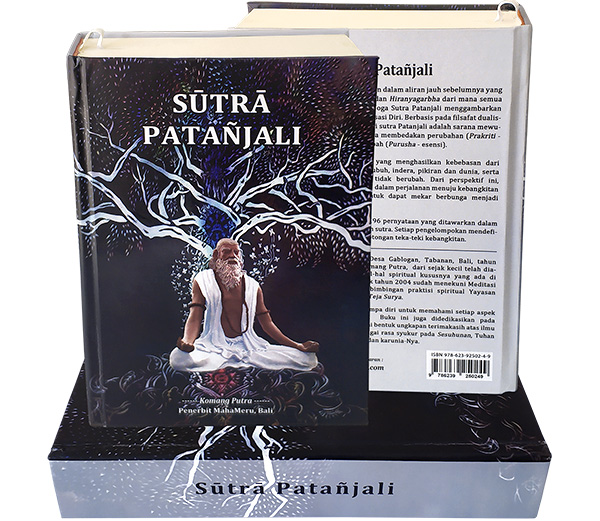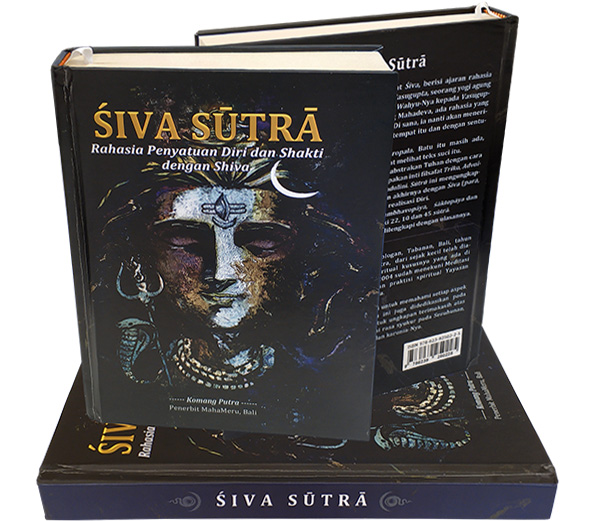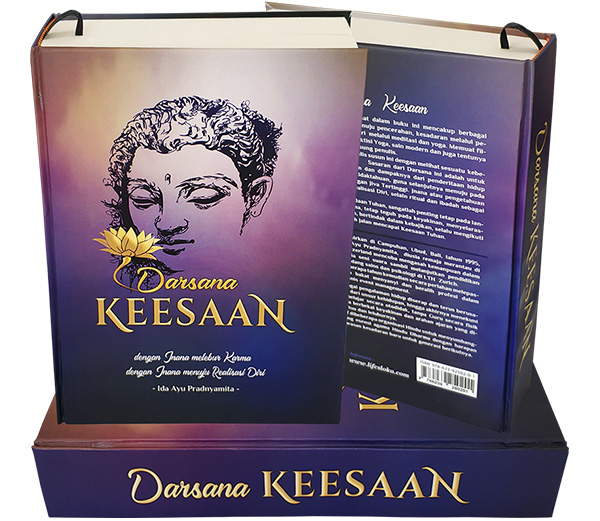1. Rasa
Rasa adalah pengalaman estetik atau emosi yang dibangkitkan secara estetik oleh lingkungan dan situasi artistik. Rasa merupakan revelasi atau pewahyuan makna esensial dari berbagai hal. Dalam revelasi atau ilham atau penerangan itulah terletak keindahan. Dikatakan bahwa, dalam rasa terjadi sublimasi emosi dari tataran psikologis ke tataran estetik.
Dalam proses sublimasi itu emosi individual ditransformasikan menjadi rasa ‘pengalaman estetik’: Individu lupa akan dirinya dan mencapai titik pandang universal yang membawa kebahagiaan tertinggi. Lewat pengalaman estetik horison seseorang diperluas. Rasa bukanlah persepsi akal budi, melainkan suatu pengalaman yang penuh kebahagiaan, sehingga pengalaman pribadi pun lenyap. Maka dikatakan bahwa pada titik itu, pengalaman estetik menjadi identik dengan pengalaman religius, yaitu bila perasaan manusia terbenam di dalam Brahman ‘Tuhan’
Rasa dialami jika orang dapat mengadakan identifikasi diri dengan barang atau peristiwa yang diamatinya. Ketika itu ia merasa takjub atau kagum. Jadi, hanya orang yang dapat merasa takjub, dapat mengalami kebahagiaan estetik. Dan kebahagian estetik itu mengandaikan tentang batin yang murni dan jernih.
Maka, ketika Mpu Kanwa melihat bayangan bulan di dalam tempayan yang berisi air jernih lalu bersyair penuh kearifan:
Sasiwimba haneng ghaþa mesi banyu,
Ndan asing suci nirmala mesi wulan,
Iwa mangkana rakwa kiteng kadadin,
Ring angambeki yoga kiteng sakalaBayangan bulan pada tempayan berisi air.
Tetapi, hanya pada tempayan yang berisi air jernih menapakkan bulan.
Seperti itulah Engkau pada setiap ciptaan.
Pada ia yang menekuni yoga Engkau nyata hadir’.
Katemunta mareka si tan katemu,
Kahidepta mareka si tan kahidep,
Kawenangta mareka si tan kawenang
Paramartha siwatwa nirawaranaMaka dijumpailah Itu yang sebelumnya tidak pernah ditemui.
Dipahamilah Itu yang sebelumnya tidak pernah dipahami.
Dialamilah Itu yang sebelumnya tidak pernah dialami.
Yaitu tujuan utama, Sang Hakikat, siwa itu tidak terhalang lagi
(Arjuna Wiwaha, XI:1)
Syair itu menunjukkan bahwa seorang mpu adalah orang yang dapat melihat; ia melihat ke dalam hakikat barang-barang dengan aneka sifatnya. “Melihat” itu semacam intuisi. Intuisi itu dilahirkan karena kontak dengan hakikat barang-barang.
Batin sang mpu terbenam seluruhnya di dalam gambar puitik lalu dilahirkan ke luar dan dipersepsi oleh pembaca. Artinya, rasa itu pertama-tama terdapat di dalam batin sang mpu, lalu ketika rasa itu telah diekspresikan dalam bentuk karya seni dan jika dinikmati oleh pembaca, maka rasa itu pun muncul pada dirinya.
Jika bhàwa ada sembilan, maka rasa pun ada sembilan. Bhàwa dan juga rasa tidak selalu tampak dalam keadaan yang murni, tetapi sering tercampur, saling berhubungan, dan bersifat sementara.
2. Agama
Dalam Kakawin Arjuna Wiwàha ditemukan kata rasàgama. Dalam tradisi mabebasan kata itu diterjemahkan dengan arti ‘intisari ajaran agama atau hakikat ajaran agama’. Akan tetapi, dalam konteks teks itu saya lebih memahaminya sebagai dua istilah yang berbeda, yaitu rasa dan àgama. Istilah àgama dimaksud lebih saya maknai sebagai tradisi suci, yaitu perilaku bajik ‘baik dan bijaksana’ seperti yang diisyaratkan oleh Mpu Kanwa dalam manggala kakawinnya (I:1):
Ambek sang paramartha pandita huwus limpad sakeng sunyata,
Tan sangkeng wisaya prayojana nira lwir sanggraheng lokika,
Siddhaning yasa wiryya donira sukaning rat kininkin nira,
Santosa helatan kelir sira sakeng sang hyang jagatkarana.Batin orang arif yang telah mencapai tujuan tertinggi telah mengatasi segalanya, karena menghayati Kesuungan.
Bukan karena terdorong oleh nafsu duniawi Beliau mencapai tujuan. (Kehadirannya) seolah-olah saja menyambut yang duniawi.
Sempurnanya jasa dan kebajikan itulah tujuan Beliau, maka kebahagiaan masyarakat itulah yang diusahakannya.
(Perbawanya) tenang sentosa, (Beliau) hanya sebatas tabir dengan Sang Pencipta Alam Semesta
Jadi, agama itu tidak semata-mata berarti teks atau doktrin suci, tetapi yang tidak kalah pentingnya justru adalah sikap dan perilaku beradab; bermoral. Apalah artinya agama tanpa tindakan bermoral.
Oleh karena itu, tradisi Bali mengatakan: “pamatin agamane tuah solah luih” ‘tanda utama seorang beragama adalah perilaku yang berperikemanusiaan’. Dan dalam konteks Hindu, perilaku bermoral itu disebut Susila. Mpu Kanwa mendefinisikan tindakan bermoral itu dengan kalimat: ” Siddhaning yasa wiryya donira sukaning rat kininkin nira ” keberhasilan dalam berbuat jasa dan kebajikan, yaitu mengusahakan kebahagian masyarakat, itulah tujuan hidup orang arif.
Keberatan saya menerima rasàgama sebagai satu istilah, karena maknanya akan berimpit dengan makna istilah yang mengikutinya yaitu buddhi têpêt. Arti istilah buddhi têpêt adalah mengacu kepada tattwa ‘ajaran hakikat; filsafat’. Tattwa inilah inti sari ajaran agama Hindu. Jadi, sama artinya dengan arti rasàgama yang dipahami dalam tradisi mabebasan selama ini.
Agama dalam arti susila memiliki sepuluh unsur, dikenal dengan istilah dasasila. Dalam kitab Saracamuscaya rinciannya: (1) Ahimsa /tidak membunuh; (2) Brahmacarya
mengendalikan nafsu /seks; (3) Satya /jujur; (4) Awyawaharika /tidak bersengketa; (5) Astenya /tidak mencuri; (6) Akrodha /tidak marah; (7) Gurususrusa /bakti kepada guru; (8) Sauca /hidup suci; (9) Aharalaghawa /mengendalikan nafsu makan; dan (10) Apramada /tidak suka mencela atau mencemooh.
Susila dalam konteks yoga, Maharsi Patanjali menyebutnya dengan istilah yama-niyama brata ‘sepuluh janji atau perilaku bajik’. Sepuluh perilaku bajik ini adalah dasar angambêki yoga ‘pelatihan yoga’.
Rinciannya sedikit berbeda dengan dasasila di atas. Yama-niyama brata sebagai berikut. (1) Ahimsa /tidak membunuh; (2) Satya /jujur; (3) Asteya /tidak mencuri; (4) Brahmacarya /mengendalikan nafsu seks; (5) Aparigraha /hidup sederhana; (6) Sauca /hidup suci; (7) Santosa /sentosa; puas; penuh rasa syukur; (8) Tapa /tahan uji; (9) Swadyaya /mempelajari kitab suci; dan (10) Iswarapranidhana /memusatkan pikiran dan bakti kepada Tuhan.
Dengan demikian, agama dimaksud dalam hubungannya dengan teks yang dibahas dapat dipahami maknanya sebagai daya karsa manusia.
3. Buddhi
Kata buddhi memiliki banyak arti. Arti leksikal yang lebih dekat hubungannya dengan pembicaraan ini, antara lain, adalah kekuatan pembentuk dan penyimpan buah pikiran, kecerdasan, akal, budi, semangat, hati, ingatan.
Buddhi adalah Tattwa, kategori kedua dari 25 unsur ajaran filsafat Samkhya, yaitu unsur psikologis yang disebut intelegensi. Fungsi buddhi adalah untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan segala apa yang datang dari alat persepsi yang lebih rendah yang disebut manas (pikiran) dan indriya (indera).
Dalam keadaan yang murni buddhi memancarkan sifat Dharma (kebajikan), Jnana (kearifan), Wairagya (ketidak-terikatan), dan Luwarya (ketuhanan).
Mpu Kanwa mengistilahkan buddhi yang murni dengan istilah buddhi têpêt ‘budi yang tepat’. Sedangkan Ida Ketoet Djelantik (1905-1961), pengarang Geguritan Sucita Subudi, menyatakannya dengan istilah subudi. Lalu budi murni itu dipersonifikasikannya dengan nama Sang Subudi, yakni tokoh pembimbing sahabatnya yang bernama Sang Sucita, personifikasi ahamkara satwika (perasaan yang baik) dua tokoh utama Geguritan Sucita Subudi. Dikatakan pula bahwa buddhi yang murni itu berada amat dekat dengan purusa (roh). Oleh karena itu, buddhi mencerminkan kesadaran roh.
Untuk memperoleh empat sifat buddhi (Dharma, Jnana, Wairagya, dan Luwarya) itu, Mahàrsi Patanjali menawarkan tiga cara melatih pikiran:
- Anumana pramana : berpikir berdasarkan penalaran empirik
- Pratyaksa pramana : berpikir berdasarkan penalaran logis
- Uabda pramana : berpikir berdasarkan teks wahyu
Berpikir dengan tiga penalaran itulah yang dimaksud dengan Buddhi tepet (berpikir benar). Sebaliknya, berpikir tanpa atas dasar bukti-bukti empirik disebut Wikalpa (menghayal); berpikir tanpa penalaran logis disebut Nidra (alpa); dan berpikir tanpa didasarkan pada teks wahyu disebut Smrti (suka mengingat yang bukan-bukan) (Yogasùtra,I:6-11).
Oleh karena itu, Mpu Kanwa menegaskan pendiriannya sekaligus menggugah kita dengan bersyair (Arjuna Wiwàha, XII:7):
Syapa kari tan temung hayu masadhana sarwa hayu,
Niyata katemwaning hala masadhana sarwa hala,
Tewas alisuh manangsaya purakreta tapa tinu,
Sakaharepan kasiddha maka darsana Pandusuta.Siapakah ia yang tidak memperoleh kerahayuan jika telah bersaranakan segala yang rahayu?
Pastilah ia memberoleh yang tidak rahayu karena bersaranakan segala yang tidak rahayu.
Memprihatinkan sekali orang yang menyangsikan purwa karma, lalu apakah yang dijadikannya pegangan hidup?
Segala cita-cita diperoleh jika mencontoh laku hidup Arjuna
Dalam syair terkutif di atas Mpu Kanwa tegas dengan keyakinannya, bahwa purwa karma atau pura kreta adalah sadhana (sarana yang baik) untuk memperoleh sarwa hayu (segala yang baik). Segala yang baik itu, dalam konteks Hindu disebut catur purusa artha (empat tujuan hidup): Dharma / Kebaikan, Artha /kekayaan, Kama /kenikmatan, dan Moksa /kebahagiaan.