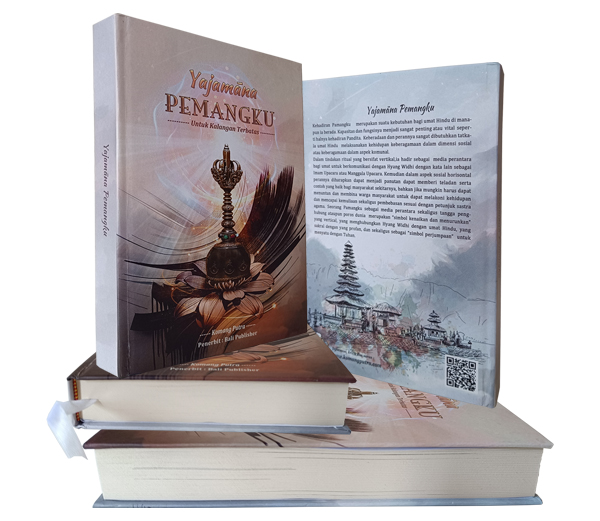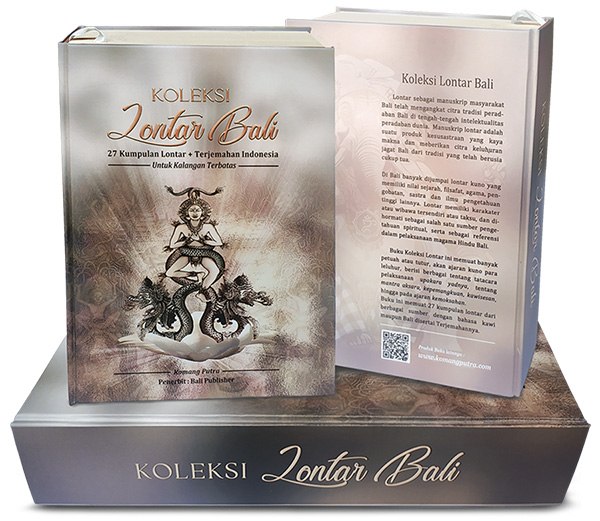- 1Īgama (Mencari Kesejatian dengan Ketajaman dan Kejernihan)
- 1.1Peranan Pikiran dalam Mistisisme Bali
- 1.2Pemanfaatan Pikiran Dalam Perjalanan Spiritual
- 1.2..11. Menajamkan daya kognisi pikiran
- 1.2..22. Mengendarai daya imajinasi dan mengarahkan ulang intensi
- 1.2..33. Melampaui keseluruhan eksistensi pikiran itu sendiri
- 2Āgama (Menata Hati, Membahagiakan Seluruh Alam)
- 2.1Menata Hati dan Kebahagiaan Seluruh Alam
- 2.2Bertuhan dengan Rasa
- 2.2..11. Bertuhan dengan Menjadi Penikmat Rasa
- 2.2..22. Mendekat Pada Tuhan dengan Menjaga Jarak Dari Rasa
- 3Ūgama (Agama, Sikap dan Kemanusiaan)
- 3.1Bertuhan Secara Sosial dan Bertuhan Secara Personal
- 3.2Bertuhan dengan Laku - Fondasi Dari Perjalanan Spiritual
Ūgama
(Agama, Sikap dan Kemanusiaan)
Aspek terakhir dari segitiga Gama Tirtha adalah Ūgama, yang adalah penataan norma kemanusiaan (ikang ugama pinaka simalokacarananing jagat). Kata lokācāra berarti cara-cara umum di masyarakat; adat dan kebiasaan. Hal ini mengacu pada kelumrahan yang berlaku dalam sebuah sistem kemasyarakatan.
Norma berarti aturan dasar tentang sikap dan perilaku baik-buruk, benar-salah, boleh-tidak boleh, yang kesemuanya adalah kesepakatan antara manusia satu dengan manusia lain. Dengan manusia sama-sama mengikuti norma yang ada, maka manusia diharapkan bisa hidup harmonis dengan sesamanya, atau setidaknya memiliki naungan umum yang akan mencegah kesemena-menaan.
Seandainya tidak ada norma yang mengatur sikap dan perilaku manusia, maka mencuri, membunuh, memperkosa, dan berbagai perbuatan biadab akan merajalela. Akhirnya, manusia akan menjadi bagaikan hewan yang hidup di hutan rimba; yang kuat memakan yang lemah. Norma lah yang menjaga peradaban agar tidak runtuh.
Mungkin berdasarkan pertimbangan sejenis ini lah maka Ūgama (yang adalah penataan hamoni kemanusiaan) dikatakan bertempat di sikap/ perilaku (Ūgama ika ring polah). Manusia tidak disebut sebagai “orang baik” atau “orang jahat” karena isi hati atau cara pikirnya, namun karena sikap dan perilaku yang ditunjukkannya. Manusia umumnya tidak bisa membaca isi hati manusia lain, yang bisa dinilainya adalah apa yang ditunjukkan melalui perilaku.
Tentu saja, dalam konteks ini kita tidak berurusan dengan kebenaran personal, juga bukan kebenaran universal, namun kebenaran komunal – artinya bukan sesuatu yang absolut benar, namun apa yang secara sosial disepakati sebagai benar. Ūgama mengajak kita menghormati kebenaran kontekstual ini, bukan malah menyuruh kita arogan memaksakan sebuah kebenaran absolut yang diyakini benar.
Saat sebuah ajaran mengatakan “agama yang benar adalah agama anu,” lalu menyuruh “ajak dan paksa semua orang agar menerima kebenaran ini” maka tentu konflik yang akan terjadi. Namun sebaliknya, karena dalam konteks Ūgama kebenaran adalah sesuatu yang sifatnya kontekstual (benar menurut siapa? Di mana? Kapan?) maka, toleransi lah yang dihasilkan.
Orang Bali memiliki prinsip desa (tempat), kala (waktu), dan patra (keadaan) dalam kaitannya dengan sikap. Sebuah sikap atau perilaku bisa menjadi benar/ salah tergantung dari ketiga elemen tersebut. Bahkan cara-cara beragama pun disarankan mengikuti prinsip tersebut. Cara beragama adalah tetap sebuah “cara” yang bersifat tradisi, dan tidak ada satu tradisi pun yang sifatnya universal (berlaku untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja), dan boleh memaksakan universalitasnya tersebut.
Menurut ajaran agama di Bali, keabsolutan adalah sebuah prinsip realitas (tattwa) yang perlu direalisasikan seorang individu, bukan sebuah cara-cara yang bisa dipaksanakan secara universal. Bahkan, prinsip-prinsip keabsolutan, baik secara teori maupun praktikanya malah cenderung dirahasiakan karena memerlukan kesiapan personal.
Bertuhan Secara Sosial dan Bertuhan Secara Personal
Di satu sisi, agama adalah konstruksi sosial, sebuah relik budaya. Sebagaimana setiap aspek kebudayaan, agama “diciptakan” oleh manusia untuk kehidupan manusia. Terlepas apakah ada peran entitas adikodrati yang memberi wahyu atau tidak, tetap saja agama dikenal manusia karena diperkenalkan oleh manusia lain.
Saat kita bicara tentang “agama” maka kita bicara mengenai teologi terstruktur yang diatur oleh lembaga keagamaan. Tiap agama memiliki lembaga agamanya sendiri. Kalaupun agama bersangkutan hanya sebatas keyakinan komunal di sebuah suku, tetap saja ada struktur sosial kesukuan tersebut yang mengontrolnya. Dengan kata lain, agama adalah konstruksi dan kesepakatan sosial. Dalam konteks sosial di Bali, tatanan religi sangat berkaitan dengan tatanan adat di masing-masing desa.
Di sisi lain, ada para mistik yang memiliki cara-caranya sendiri dalam bertuhan. Kadang ia memiliki pandangan dan cara yang malah berseberangan dengan cara-cara yang dianggap normal secara sosial. Bahkan tidak jarang juga kitab-kitab mistik mengkritisi cara-cara yang secara sosial dianggap normal.
Namun satu hal yang perlu diingat adalah, para mistik ini umumnya telah melepaskan diri dari ikatan sosial. Dalam artian, mereka adalah para pertapa di hutan dan gunung, atau di tempat khusus lain. Pandangan ketuhanan yang mereka anut pun bersifat ekslusif. Para mistik ini memegang ajaran yang sifatnya esoterik – ajaran yang dirahasiakan dari publik dan hanya diturunkan untuk para murid yang telah dinilai siap menerimanya.
Karena para mistik memegang dan mengimplementasikan ajarannya secara personal, bukan memaksakannya secara sosial, maka tidak ada konflik yang terjadi. Bahkan masyarakat sosial umumnya menghormati para mistik karena telah mendedikasikan diri terhadap jalan spiritual tertentu.
Namun jika yang terjadi adalah kebalikannya, maka konflik tidak akan bisa dihindari. Karena tidak semua ajaran ditujukan untuk semua orang. Ajaran-ajaran para yogi, para mistik, para Tantrika adalah khusus bagi mereka, bukan konsumsi publik. Namun sebaliknya, aturan norma sifatnya mengikat dan merupakan sebuah keharusan untuk semua yang menjadi bagian di dalamnya.
Seorang pendeta yang menjadi yogi di hutan belantara tidak harus mengikuti aturan di Desa Anu, sebab ia hidup bebas dan lepas dari tatanan Desa Anu. Namun, seorang pendeta yang masih menjadi bagian dari Desa Anu tetap harus mengikuti aturan-aturan di desa tersebut – tetap mengikuti etika yang dijadikan standar di desa tersebut.
Garis-garis ini penting diketahui sebelum seseorang memutuskan mengikat diri dalam sebuah komitmen spiritual. Jika merujuk pada kasus-kasus belakangan, contohnya adalah; seorang pendeta yang dinilai bertindak asusila, dari sisi apa pun. Pendeta bersangkutan bisa saja mengelak dengan mengatakan bahwa yang dia lakukan adalah yang dia yakini, bahwa itu lah nilai-nilai yang dia anut. Namun, pendeta tersebut akan tetap salah, jika nilai yang dianutnya ternyata bertabrakan dengan norma kesusilaan yang berlaku secara sosial. Dia hanya bebas dengan nilai personalnya di tataran personal, bukan mempertontonkannya di tataran sosial.
Demikian pula halnya meyakini Istadewata tertentu (dan memujanya dengan cara tertentu). Semua itu adalah sebuah pilihan pribadi dan sebuah cara beragama yang sifatnya personal. Namun, mempertentangkannya dengan norma sosial tetap adalah sebuah kesalahan, dari sudut pandang sosial.
Garis pembatas antara beragama personal dan tatanan sosial adalah sebuah garis yang jelas. Sayangnya, sering kali banyak orang gagal melihat garis ini, sehingga kemudian memunculkan banyak gesekan-gesekan. Semua ini bukan melulu soal Tuhan, namun tentang manusia dan tatanan yang disepakatinya sebagai cara berkehidupan. Hidup dalam kelompok manusia itu berarti harus mengikuti kesepakatan kelompok tersebut (terlepas dari penilaian personal benar-salah terkait aturan tersebut). Jika tidak, maka berbagai sanksi yang juga sudah diatur akan diterima. Namun keharusan ini ada di tataran sosial itu sendiri. Secara personal, seseorang tetap bebas dengan keyakinan, pemikiran, dan cara-cara personalnya (selama tidak bersinggungan dengan sosial).
Ūgama bukanlah cara agar “dicintai Tuhan,” dalam artian berperilaku baik karena Tuhan menyukainya, Kita melakukan hal-hal baik dan bersikap baik demi kemanusiaan – demi menjaga tatanan harmoni antar manusia. Bukan Tuhan yang perlu dijadikan pertimbangan, melainkan kehidupan antar manusia. Bahkan dalam teksnya pun dikatakan bahwa Ūgama adalah untuk “harmoni kemanusiaan.”
Berpikir bahwa apa-apa adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan mungkin bukan lah hal yang keliru. Hanya saja, jangan sampai hal ini membuat kita lupa bahwa dengan kehidupan, bumi, dan kemanusiaan. Contohnya, seorang pengemis yang sangat religius mendapat sumbangan besar dari seorang yang sangat dermawan, alih-alih mengatakan terimakasih pada orang itu, dia malah sujud syukur pada Tuhan, dan mengabaikan orang yang memberinya sumbangan. Padahal, akan lebih etis jika dia mengucap terimakasih pada orang itu, baru kemudian bersyukur pada Tuhan. Alam dan manusia adalah Bhaṭāra Sakala (Tuhan dalam wujud nyata), artinya berkemanusiaan adalah cara nyata bertuhan.
Ūgama sebagai “cara bersikap” yang sesuai dengan “tatanan sosial” juga adalah sebuah penegasan terhadap fleksibilitas. Ūgama tidak berurusan dengan cara-cara bersikap yang benar secara universal, namun benar dalam konteks-konteks tertentu. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kita diajak untuk menghormati kebenaran bersikap dalam konteks (wilayah) lain.
Bertuhan dengan Laku – Fondasi Dari Perjalanan Spiritual
Dalam Lontar Wrahaspati Tattwa disebutkan bahwa yang menjaga seorang yogi dalam samadhi-nya adalah Tapabrata. Sementara dalam Lontar Tattwajñāna disebutkan bahwa Tapabrata adalah fondasi dari perjalanan yoga (prayogasandhi). Demikian pula dalam sistem yoga Astangga-yoga dari Rsi Patanjali, penataan sikap menjadi fondasi utama, yang diatur dalam dua tahap awal yoga, yaitu Yama dan Niyama. Tapabrata adalah tentang bagaimana kita bersikap terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap semua hal yang ada.
Manusia memiliki kehausan spiritual yang kemudian diekspresikan dalam sikap religius seperti sembahyang dan berbagai ritual keagamaan lain. Dari kehausan spiritual pula muncul keinginan untuk belajar mengenal-Nya. Namun keduanya belum lah cukup.
Āgama dalam konteks Āgama Bali tidak hanya terdiri dari Teologi (ilmu tentang tuhan) dan Liturgi (ritual berketuhanan), melainkan perlu ada sikap nyata yang menunjukkan semua itu – sikap nyata yang ditunjukkan dalam kehidupan.
Dari sisi filosofis dijelaskan bahwa Bhaṭāra bersifat niskala (halus, melampaui semua yang berwujud), juga niskala (mewujud menjadi semua yang ada). Dengan demikian, semua yang ada ini (manusia, binatang, tumbuhan, dan seluruh alam) merupakan personifikasi nyata dari Bhaṭāra. Karenanya, bukan hanya di tempat suci, bukan hanya pada patung-patung sakral (pratima/ arca/ murti) Bhaṭāra diwujudkan dan dihayati keberadaanya, namun juga pada semua yang hidup.
Ajaran Ūgama mengajak kita untuk menubuhkan ajaran suci – mengaktualisasikan kebaikan yang diketahui dan dirasakan menjadi aksi nyata. Tujuannya, bukan untuk Tuhan “di sana” melainkan untuk Bhaṭāra Sakala (kehidupan dan seluruh aspeknya). Melalui sisi Ūgama dari Gama Tirtha, kita sedang diajak untuk bertuhan dengan berkemanusiaan.