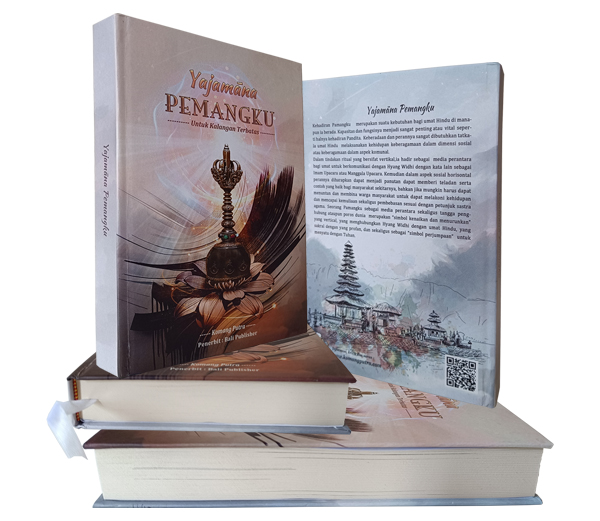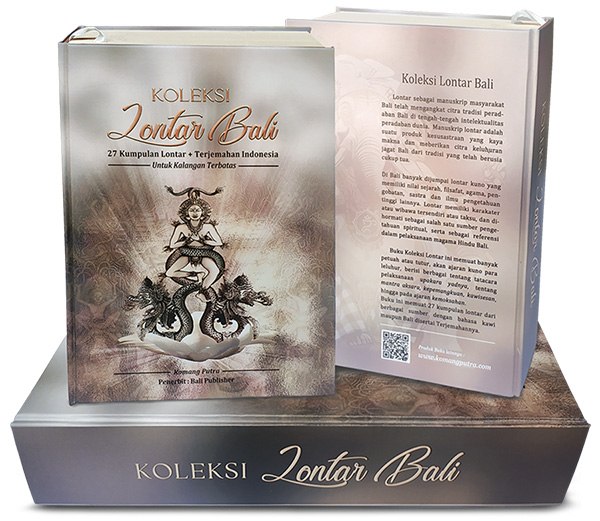- 1Īgama (Mencari Kesejatian dengan Ketajaman dan Kejernihan)
- 1.1Peranan Pikiran dalam Mistisisme Bali
- 1.2Pemanfaatan Pikiran Dalam Perjalanan Spiritual
- 1.2..11. Menajamkan daya kognisi pikiran
- 1.2..22. Mengendarai daya imajinasi dan mengarahkan ulang intensi
- 1.2..33. Melampaui keseluruhan eksistensi pikiran itu sendiri
- 2Āgama (Menata Hati, Membahagiakan Seluruh Alam)
- 2.1Menata Hati dan Kebahagiaan Seluruh Alam
- 2.2Bertuhan dengan Rasa
- 2.2..11. Bertuhan dengan Menjadi Penikmat Rasa
- 2.2..22. Mendekat Pada Tuhan dengan Menjaga Jarak Dari Rasa
- 3Ūgama (Agama, Sikap dan Kemanusiaan)
- 3.1Bertuhan Secara Sosial dan Bertuhan Secara Personal
- 3.2Bertuhan dengan Laku - Fondasi Dari Perjalanan Spiritual
Āgama
(Menata Hati, Membahagiakan Seluruh Alam)
Sisi kedua dari segitiga Gama Tirtha adalah Āgama. Dijelaskan bahwa Āgama adalah hal-hal terkait penciptaan harmoni dengan lingkungan dan alam (pakṛtining jagatmanḍala). Yang disebut dengan jagat mandala adalah alam tempat kita hidup. Hutan, pegunungan, danau, laut, sawah, lingkungan desa/ komplek perumahan, semua itu lah mandala suci tempat kita hidup. Jika dia bahagia, maka kita berbahagia; jika dia hancur, maka kita yang ada di dalamnya pun hancur.
Dijelaskan pula bahwa Āgama berada di tataran ambĕk. Kata ambĕk dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno didefinisikan sebagai; batin manusia, pikiran atau perasaan (yang menjadi tempat berbagai emosi, suasana hati, dan kecenderungan), watak atau sikap batin (sebagai lawan dari perilaku eksternal), karakter, watak, dorongan batin, keinginan, dan niat. Dalam tulisan ini, ambĕk akan diterjemahkan sebagai batin dan hati manusia.
Sementara iḍĕp terkait dengan pemikiran, maka ambĕk terkait dengan perasaan. Jika iḍĕp adalah intelegensi, maka ambĕk adalah hati. Tidak susah memahami ambĕk dengan memahami bagaimana kata “hati” dipakai masyarakat Indonesia saat ini, seperti; kata hati, dorongan hati, berhati lembut, berhati jahat, tidak punya hati, suasana hati, hatinya hancur, jatuh hati, patah hati, berhati lapang, berhati busuk, dan sederet lainnya.
Dari kacamata Psikologi Modern istilah rasa, emosi, mood, kognisi, temperamen, dan seterusnya masing-masing memiliki arti yang berbeda-beda. Meski garis pembatas yang membedakan masing-masing elemen masih menjadi bahan perdebatan. Bahkan batasan antara emosi dan rasa pun terkadang abu-abu dan menjadi bahan diskusi hangat. Namun dalam tulisan ini, istilah “rasa” dan “emosi” akan digunakan saling beriringan, saling menggantikan.
Sebagaimana dunia luar, dunia batin (ambĕk) adalah objek pengalaman Sang Kesadaran (Purusha). Jika secara eksternal manusia mengalami dunia luar dengan berbagai warna-warni, bentuk, dan lika-likunya, secara internal manusia mengalami dunia batin dengan berbagai gejolaknya.
Lalu apa hubungan antara menata alam dengan menata hati? Apa hubungan antara pakṛtining jagatmanḍala dengan ambĕk?
Manusia akan memperlakukan semua hal (diri, orang lain, dan alam) sesuai dengan isi hatinya. Sebagai contoh, seorang dengan hati yang serakah akan cenderung semena-mena dan mengeksploitasi alam. Keegoisannya akan membuatnya abai dengan konsekwensi dari sikapnya itu, dan akhirnya alam menjadi rusak. Sementara orang-orang dengan hati yang lembut dan penuh cinta akan cenderung memelihara alam, sehingga alam kemudian menjadi ruang yang semakin mendamaikan hatinya.
Karenanya, perjalanan spiritual dan hidup berketuhanan adalah tentang “menata hati.” Dalam berbagai pustaka yang ada disebutkan berbagai tatanan hati yang perlu dibangun oleh seorang pejalan spiritual. Hati disucikan, dilembutkan, diisi dengan welas asih dan kebajikan, dan darinya pikiran pun akan menjadi tenang, kemudian sikap kita terhadap berbagai hal pun akan mencerminkan semua itu.
Hal ini menjadi sebuah aspek penting dari Gama Bali yang perlu dibatinkan. Jangan sampai belajar spiritual hanya fokus menajamkan intelegensi, tapi lupa menata hati. Akhirnya, tajamnya kecerdasan yang dimiliki malah dipakai sebagai senjata oleh ego. Dampaknya, bukannya semakin berbahagia, pembelajaran spiritual malah akan semakin menyengsarakan dan memenjarakan.
Menata Hati dan Kebahagiaan Seluruh Alam
Āgama adalah tentang menata hati. Dalam pustaka-pustaka Tattwa disebutkan bahwa hati tempat suci tempat Bhaṭāra bersemayam. Karenanya, kesucian hati perlu senantiasa dijaga, dan berbagai hal yang mengotorinya perlu dipangkas.
Jika dikaitkan dengan kebahagiaan alam, salah satu kondisi batin yang disarankan untuk dikembangkan adalah ambĕk samatā (hati yang tidak membeda-bedakan) – memandang sama antara semua mahluk, semua orang, semua hal. Diumpamakan oleh teks Wratiśāsana seperti matahari yang menyinari semua mahluk tanpa pandang bulu. Kondisi batin ini adalah kebalikan dari kondisi batin harian kita pada umumnya yang penuh diskriminasi.
Kadang kita membeda-bedakan antara satu orang dengan orang lain; ada orang yang dibenci, ada yang dicintai; ada orang yang dijunjung tinggi, ada yang direndahkan, dan seterusnya. Kita pun cenderung membeda-bedakan antara satu mahluk dengan mahluk lain; memandang manusia mahluk yang tinggi derajatnya, dan binatang serta hewan jauh di bawah. Batin seperti ini tidak jarang kemudian terekspresikan menjadi sikap eksploitatif dan sewenang-wenang terhadap alam dan isinya.
Batin yang memandang sama antara semua juga adalah batin yang sedang beryoga, sebagaimana yoga yang didefinisikan oleh Bhagavad Gita.
Eksistensi manusia dan alam tidak memiliki hirarki absolut. Tentu saja, Shastra juga mengajarkan bahwa manusia memiliki posisi unik, sebab manusia memiliki rasio dan rasa, serta bisa mengolah keduanya untuk menata kehidupannya sendiri. Namun demikian, dari sisi eksistensi, manusia dan alam bersifat co-exist (sama-sama ada, saling tergantung satu dengan yang lain; saling membutuhkan, saling menjaga). Baik manusia, binatang, dan tumbuhan adalah bagian dari kehidupan.
Karena tidak menyadari bahwa kita co-exist bersama aspek kehidupan lain, maka kita kemudian tergoda untuk bersikap semena-mena. Hal ini lah yang membuat manusia mengeksploitasi alam yang kemudian membawa bencana pada manusia itu sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa alam. Bahkan, berkat alam lah manusia bisa ada sebagaimana adanya sekarang.
Sebuah kisah dari garis evolusi manusia di jaman pra-sejarah menyebutkan, pada awalnya, leluhur manusia dan kera adalah sejenis primata yang hidup di atas pohon. Primata ini melompat dari satu pohon ke pohon lain dengan mengandalkan tangan. Pepohonan jaman pra-sejarah demikian lebat, jarak tumbuhnya saling berdempetan. Semua makanan tercukupi di pepohonan, sehingga primata tersebut tidak pernah turun dari pohon.
Namun, seiring perkembangan jaman, maka tumbuh lah rumput di mana-mana. Lebatnya rumput kemudian membuat jarak dari satu pohon dengan pohon lain semakin berjauhan. Karena jarak yang semakin berjauhan tersebut, primata yang tadinya bisa menjangkau satu pohon dari pohon lain dengan tangan tidak lagi bisa melakukannya. Mau tidak mau, para primata ini pun kemudian turun dari pohon, dan belajar menggunakan kakinya. Dari sana lah kemudian primata ini belajar berdiri dan berjalan, dan ini lah asal-usul manusia purba yang menjadi cikal-bakal manusia kemudian.
Dari cerita ini beberapa hal bisa direnungi; alam adalah “kakak” yang mendidik dan menjaga kita. Alam juga adalah “ibu” yang melahirkan manusia. Perlu waktu jutaan tahun untuk alam berkembang, dari gumpalan bola api sampai kemudian menjadi planet bernama bumi yang kaya dengan kehidupan. Dari mahluk ber-sel tunggal di bawah laut menjadi beragam fauna. Namun, hanya dalam beberapa ribu tahun perkembangan manusia modern cukup untuk merusak alam sampai titik tak terbenahi lagi.
Ada lah pilihan manusia untuk mengakui kita hidup beriringan (co-exist) bersama alam, atau bersikap jumawa dan sewenang-wenang pada alam, yang kemudian tentunya sikap ini akan menjadi boomerang. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam, sedangkan alam akan tetap berlangsung tanpa spesies bernama manusia. Kehidupan telah menyaksikan berbagai kepunahan mahluk, termasuk kepunahan mahluk-mahluk mengagumkan bernama Dinosaurus. Namun, meski Dinosaurus kini hanya tinggal belulang dan kenangan, alam tetap hidup, berlanjut, memberi ruang untuk mahluk lain berkehidupan.
Dalam tradisi Bali, ada banyak mitologi dan liturgi terkait pentingnya penataan alam. Contohnya, ajaran Kanda Mpat yang menempatkan aspek-aspek alam sebagai “kakak kandung” manusia. Dari segi liturgi, ada berbagai hari raya dan ritual penataan dan penghormatan alam; mulai dari Hari Tumpek Pangatag, Hari Tumpek Kandang, Ritual Ngusaba Desa, dan berbagai jenis Ritual Ngusaba lain, serta ajaran tentang Sad Kerti, dan banyak lagi. Semua mitologi dan liturgi ini adalah pesan bahwa kita hidup beriringan dengan alam, saling menjaga dan saling menghidupi. Pesan ini tidak akan ada gunanya jika ia tidak dibaca, atau pun kalau dibaca tapi tidak ditindaklanjuti dengan aksi nyata.
Āgama adanya di ambĕk, dan ambĕk adalah rasa. Dari rasa lahir lah sikap. Saat kita memiliki rasa cinta dan hormat, maka muncul sikap merawat. Saat rasa angkuh jumawa mendominasi, maka sikap mengeksploitasi lah yang lahir. Contoh paling sederhana, jika kita mencintai tanaman di taman, maka kita akan rajin menyiraminya, merawat dan melindunginya. Berkat taman yang terawat, maka keindahan pun muncul, kesegaran mata dan udara tercipta, hati pun menjadi tenang. Dan ini lah “krthi (keharmonisan)” sederhana yang menjadi lingkaran kerahayuan.
Bertuhan dengan Rasa
Pikiran membuat kita mengetahui dan hati membuat kita merasakan. Saat kita mengetahui sesuatu secara rasional, pengetahuan tersebut masih di permukaan. Namun saat kita merasakan apa yang diketahui tersebut, maka ia meresap semakin dalam di sanubari. Sebagai contoh, kita bisa mengetahui bahwa alam semesta secara esensial adalah tunggal. Pengetahuan ini bisa jadi muncul sebagai hasil bacaan, ceramah, dan seterusnya. Namun, selama pengetahuan itu belum menyentuh tataran rasa, maka kita belum akan mengalami apa yang kita ketahui tersebut.
Dalam tataran tertentu, Āgama Bali adalah agama rasa. Elemen-elemen budaya religius yang ada di Bali dirancang sedemikian rupa sebagai media olah rasa. Dalam kaitannya dengan olah rasa, dalam tradisi spiritual Bali bisa ditemukan dua cara dalam menata rasa; pertama, menikmati rasa; kedua, menjaga jarak dari rasa.
1. Bertuhan dengan Menjadi Penikmat Rasa
Dalam kaitannya dengan menikmati rasa, kita bisa melihat implementasinya dalam dalam kesenian. Di Bali seni selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual keagamaan dan berkehidupan. Mulai dari seni olah suara (Kidung, Kakawin, Geguritan, dll), seni tari, seni lukis (rerajahan), dan musik (gambelan). Rasa dinikmati di seluruh indera; telinga mendengarkan kemerduan lagu dan musik, mata melihat pemandangan penuh warna-warna (seperti banten gebogan, berbagai tetandingan, dan pernak-pernik penghias Pura), dan bahkan lidah pun mengecap rasa yang nikmat (berbagai olahan yang dibuat selama ritual).
Seni adalah media perangsang rasa. Melalui kesenian, masyarakat Bali melakukan olah rasa. Seni membangkitkan berbagai sensasi emosional yang membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman religius yang hendak dicapai; mulai dari rasa keindahan, rasa bahagia dan suka cita, rasa takjub (lango), dan perasaan lain.
Selain rasa yang nikmat, rasa yang “kurang nyaman” pun menjadi bagian dari religi; rasa rindu dengan Sang Kesejatian karena sadar diri “terpisah” dari-Nya, dan rasa ingin bertemu dan mengalami Dia yang dicintai. Bahkan juga rasa takut dan ngeri pun terkalibrasikan selama ritual — misalkan saat Ritual Caru, Calonarang, dan sejenisnya. Rasa takut dan ngeri ini membuat kita merasa kecil diantara berbagai daya semesta yang ada, dan dari rasa ini kemudian tumbuh rasa takjub dan hormat pada semua eksistensi, sakala dan niskala.
Rasa bukan hanya menyangkut perasaan , bukan hanya bersifat mental, namun juga fisik, yaitu berbagai sensasi yang dirasakan di tubuh. Dalam kaitannya dengan sensasi rasa di tubuh banyak cara orang Bali dalam merayakan rasa. Salah satunya adalah dengan olah masakan, dengan berbagai bumbu yang menyengat dan kaya rasa. Masak-masak (maebat) adalah bagian tak terpisahkan dari berbagai ritual yang diselenggarakan di Bali. Masakan yang dibuat bukan hanya ditujukan sebagai persembahan, melainkan juga hidangan.
Selain rasa di lidah yang dipuaskan dengan masakan, kenikmatan rasa ragawi lain dicapai pula melalui seksualitas. Ajaran di Bali adalah ajaran yang bersikap positif terhadap seks. Tentu saja, tidak ada aktifitas seksual yang sifatnya literal dalam religi komunal ataupun ritual mistik. Seksualitas literal tetap merupakan konsumsi sepasang individu, sedangkan di tataran religi seksualitas bersifat simbolik.
Beragama adalah sebuah aktifitas yang menyenangkan dan penuh sukacita, selayaknya festival. Tarian, nyanyian, gelak tawa, pertunjukan, makanan, semua tersaji sebagai pemuas rasa.
Sikap beragama selayaknya “berpesta” dan penuh suka-cita ini juga ditunjukkan oleh para Kawi Wiku (pendeta pengarang), yang biasanya adalah para traveller. Mereka berpetualang mengunjungi berbagai tempat, menikmati keindahannya, lalu mengabadikan keindahan tersebut dalam tembang yang dituliskannya.
Biasanya, beragama senantiasa dikonotasikan sebagai kebalikan dari suka-cita dan kesenangan. Bahkan tidak jarang, berpesta dan bersenang-senang dilabeli sebagai hal-hal yang membuat kita merasa berdosa. Tentu saja, bagi para pendeta dan pertapa yang sudah memasuki fase lepas dari keduniawian hal ini benar. Namun demikian, bagi kalangan kebanyakan, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat.
Pustaka Jñānasiddhānta mengatakan sendiri menuliskan, bahwa dengan memuaskan rasa di tataran inderawi maka Bhaṭāra akan disenangkan. Dengan kata lain, bersenang-senang adalah cara bertuhan. Suka-cita perlu dinikmati, namun tetap saja, jangan sampai dia menenggelamkan dan memenjarakan. Menemukan batas antara “mengendalikan dorongan inderawi” dan berpesta pora adalah hal yang tidak mudah. Namun, tanpa memaksudkannya sebagai kalimat imperatif, satu hal yang perlu diingat adalah, bertuhan tidak harus menjadi aktifitas yang membosankan, menjemukan, kaku, “tua,” dan jauh dari kesenangan.
2. Mendekat Pada Tuhan dengan Menjaga Jarak Dari Rasa
Setelah merenungi bagaimana bertuhan dengan menjadi penikmat, sisi lain yang juga perlu direnungi adalah bagaimana mendekat pada Tuhan dengan menjaga jarak dari rasa. Hal ini biasanya menjadi cara-cara yang digunakan oleh para mistik. Para yogi, para pertapa, dan para pendeta, mereka adalah orang-orang yang secara tekun menata rasa, selain secara ekspresif juga dengan melatih diri untuk berjarak dengan rasa.
Rasa atau emosi dalam teks-teks Tattwa dipandang sebagai bagian dari Prakrti, dan tujuan dari perjalanan spiritual adalah memisakan Purusha (kesadaran) dari obejeknya (Prakrti). Dengan demikian, latihan menjaga jarak dari rasa adalah cara untuk memurnikan Sang Kesadaran.
Dalam Pustaka Ślokāntara disebutkan bahwa Tapa adalah praktik “tidak membeda-bedakan rasa (tapa ṅa ambĕk kawiratin).” Pustaka Ślokāntara tidak sedang mengajak kita untuk “memusuhi” kondisi emosional tertentu dan mengidealkan kondisi lainnya. Bukan juga berarti kita diajak berperang dengan perasaan kita sendiri.
Kata wirat berarti “tidak tertarik” juga berarti “memandang secara sama.” Dalam pandangan seekor singa kelaparan, baik rusa maupun kelinci adalah sama saja, sama-sama makanan. Demikian pula dalam pandangan seorang pertapa hutan, bongkahan permata atau batu sungai adalah sama saja, sama-sama tidak memunculkan gairah memiliki. Dari konteks ini, kita diajak untuk tidak membeda-bedakan kondisi emosional — terlalu mengagungkan rasa nyaman dan mendiskreditkan rasa tidak nyaman; terlalu terobsesi dengan kondisi emosional yang menikmatkan, dan takut dengan kondisi sebaliknya.
Deskripsi ini sejalan dengan praktik mindfullness yang sekarang banyak dilatih di seluruh belahan dunia. Dalam praktik mindfulness, kita diajak untuk menjadi pengamat, termasuk di dalamnya mengamati rasa; saat muncul rasa nyaman dalam diri, kita mengamati tanpa menilainya sebagai baik atau pun buruk; demikian pula saat muncul kondisi-kondisi emosional yang tidak menyamankan, kita bereaksi dengan batin yang sama. Kita belajar melatih batin yang sama, tidak membeda-bedakan satu pengalaman dengan pengalaman lain, menjadi netral, ibarat duduk di tepi sungai alih-alih hanyut oleh arusnya.
Ada kalanya kita belajar mengekspresikan berbagai rasa, mengenalinya lebih dekat, dan menari bersamanya. Namun ada kalanya kita berlatih untuk menata jalur irigasi rasa. Manusia umumnya cenderung menginginkan rasa-rasa yang menyenangkan (puas, nyaman, cinta, dll) dan menghindari rasa-rasa yang tidak menyamankan (sedih, marah, gundah, kecewa, dll). Tidak jarang pula manusia melakukan hal-hal buruk karena obsesinya terhadap rasa, rela melakukan apa pun demi menikmati sensasi rasa tertentu yang diidamkan. Mereka ini adalah budak-budak rasa. Karenanya, Ślokāntara mengingatkan untuk melatih diri berada di atas rasa, menjadi pengendali rasa, bukan malah menjadi budaknya.