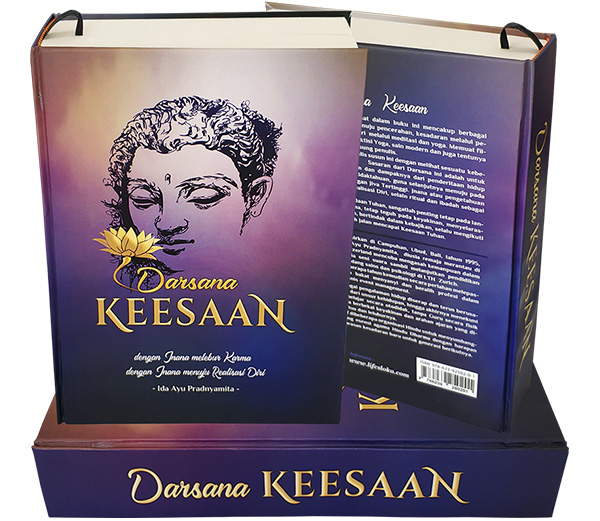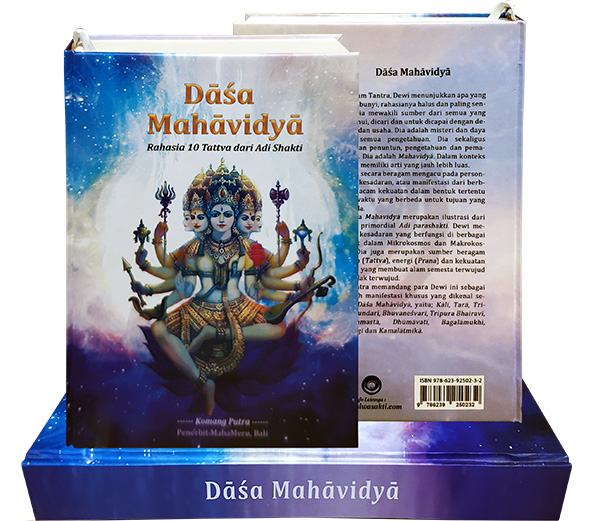- 1Ajeg Bali Melalui Tri Hita Karana
- 2Filosofi Tri Hita Karana
- 3Sisi Perdamaian dan Konflik "Budaya" di Bali
- 4Kebutuhan Menahan Diri
- 5Tri Hita Karana dalam Praktek
- 5.1Sradha sebagai wujud aspek Parhyangan
- 5.2Bhakti sebagai wujud aspek Pawongan
- 5.3Cinta Kasih sebagai wujud aspek Palemahan
- 6Pelestarian Lingkungan Saat Hari Raya
- 6.1Implemantasi Tri Hita Karana pada Tumpek Pengarah
- 6.1Makna Teologis
- 6.2Makna Ekoreligi
- 6.3Makna Pendidikan Komunikasi Dengan Tumbuh-Tumbuhan
- 6.4Makna Sosio Kultural
- 7Harminisasi dengan Konsep Sanga Mandala
Ajeg Bali Melalui Tri Hita Karana
Tri Hita Karana adalah salah satu latar belakang filosofis dasar di balik program Ajeg Bali di Bali. Ajeg Bali adalah istilah yang dipopulerkan oleh Bali Post Media Group di Bali terutama setelah musibah Bom Bali 2002. Diyakini bahwa penderitaan Bom Bali 2002 terjadi karena “orang Bali telah melupakan diri mereka sendiri dan telah meninggalkan sifat asli mereka, karena eksploitasi fisik dan spiritual yang disebabkan oleh pariwisata. Eksploitasi ini pada gilirannya diidentifikasi sebagai penyebab utama krisis ekonomi yang dihadapi Bali, khususnya setelah pemboman ”(Palermo, 2005, hlm. 243).
Menghadapi musibah dan keputusasaan dari Bom Bali 2002, orang-orang Bali berusaha mengembalikan kondisi damai tanah mereka. Solusinya terletak pada ajaran Hindu sebagai agama mayoritas di Bali yang mengkristal dalam istilah “Ajeg Bali”. “Ajeg Bali” berusaha mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Bali yang dihancurkan oleh bom dan juga efek negatif dari pariwisata. Dalam pencarian “keseimbangan”, orang-orang Bali — yang dipromosikan oleh pemerintah dan media khususnya kelompok Bali Post menemukan bahwa Tri Hita Karana akan menjadi solusi terbaik untuk masalah mereka. Singkatnya, kampanye “Ajeg Bali” adalah yang membawa makna dan kebutuhan akan konsep Tri Hita Karana sebagai pedoman spiritual untuk mengembalikan perdamaian di Bali.
Sejarah Tri Hita Karana sendiri berasal sebelum istilah “Ajeg Bali” diciptakan. Ini pertama kali diperkenalkan di Konferensi Daerah I Badan Perjuangan Umat Hindu Bali yang diadakan di Perguruan Dwijendra Denpasar. Peristiwa ini terjadi pada 11 November 1966. Roth dan Sedana berpendapat bahwa Tri Hita Karana berasal dari filosofi organisasi yang disebut Prajaniti Hindu Indonesia pada 1960-an (Sedana, 2015, hlm. 164).
Tulisan ini akan mencoba melihat filosofi Tri Hita Karana dalam memengaruhi kehidupan masyarakat Bali. Tri Hita Karana mendesak masyarakat Bali untuk hidup damai dan menciptakan harmoni dengan lingkungan mereka. Makalah ini akan mendekati filosofi Tri Hita Karana dengan perspektif studi perdamaian. Teori perdamaian akan mencari gambaran yang lebih besar dalam menganalisis konflik dengan mencari akar penyebab konflik dalam masyarakat dari nilai dan keyakinan yang mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Filosofi Tri Hita Karana
Tri Hita Karana yang terdiri dari 3 kata = “Tri” (tiga), “Hita” (kebahagiaan / kesejahteraan), dan “Karana” (penyebab) maka itu berarti “tiga penyebab kebahagiaan”. Ajaran ini percaya bahwa manusia dapat mengejar kebahagiaan mereka melalui tiga cara yang harmonis: harmoni dengan Tuhan (Parahyangan), harmoni dengan sesama manusia (Pawongan), dan harmoni dengan alam (Palemahan). Kunci untuk mencari kebahagiaan melalui Tri Hita Karana adalah hubungan yang seimbang dalam ketiga bidang ini.
Konsep Tri Hita Karana mermula dari Bhagavadgita III.10 (Mantra, 1981, hal. 42):
“Di masa lalu, ketika Prajapati menciptakan manusia dengan Yadnya dan berkata; dengan Yadnya, Anda akan bangkit dan akan menjadi Kamadhuk [sapi suci Dewa Indra yang dapat memenuhi segala keinginan] dari keinginan Anda ”
Dari Sloka ini, kita dapat menemukan dua elemen utama Tri Hita Karana: Prajapati (Dewa) dan Praja (manusia). Inti dari Tri Hita Karana terletak pada tiga aspek: etika antroposentrisme (berbasis manusia), etika ekosentrisme (berbasis alam), dan etika toposentris. Etika dengan demikian menuntun manusia pada satu kata: menahan diri. Orang Bali selalu mengatakan untuk tidak menjadi orang yang disepakati (Lobha) karena hal itu secara otomatis akan memicu banyak konflik. Jika seseorang bertindak tamak dalam komunitasnya, mereka cenderung mengambil alih apa yang bukan haknya dan tidak diragukan lagi mengundang tanggapan negatif dari orang-orang yang haknya diambil. Hal yang sama berlaku untuk hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Jika seseorang bertindak tamak dan mengeksploitasi alam di luar batas, itu akan mengakibatkan bencana. Di sisi lain, manusia harus menyadari hubungan vertikal mereka dengan Tuhan, karena manusia adalah entitas yang “lebih rendah” di bawah Parahyangan.
Tri Hita Karana menggarisbawahi “keseimbangan” dalam kehidupan Manusia. Pertanyaan utamanya adalah: bagaimana orang-orang akan menempatkan diri mereka di antara “Dunia” (makrokosmos – sifat dasar ibu, lingkungan dan Tuhan itu sendiri) dan “dunia” (mikrokosmos / dan keberadaannya sebagai manusia). Keseimbangan antara faktor-faktor ini akan membawa manusia ke dalam kondisi moksartham jagadhita ya caiti dharma atau kebahagiaan holistik baik dari sisi spiritual maupun materi manusia.
Hubungan dengan Tuhan menciptakan Parahyangan atau hubungan spiritual antara Pencipta dan ciptaan. Parahyangan (Hyang = Tuhan) berisi hubungan horizontal di mana manusia harus menunjukkan “Bhakti” (kesediaan untuk mematuhi) kepada Tuhan. Parahyangan juga menjadi fondasi ritual Hindu yang berfungsi sebagai simbol kepatuhan mereka terhadap Pencipta.
Pawongan (Wong = manusia) berasal dari filosofi Tat Twam Asi yang secara harfiah berarti “Aku adalah Kamu”. Ajaran ini mengajarkan bahwa semua manusia sama sama sehingga manusia harus memperlakukan orang lain seperti bagaimana mereka ingin diperlakukan atau. Singkatnya, Tat Twam Asi berarti “memanusiakan manusia”. Hubungan dengan lingkungan tersebut menciptakan pawongan atau hubungan sosial antara sesama manusia. Pawongan kemudian dapat dipraktikkan dengan melakukan Tri Kaya Parisudha atau “tiga kebiasaan baik” yang terdiri dari Manacika (berpikir baik), Wacika (berbicara baik), dan Kayika (berakting baik).
Terakhir, hubungan antara manusia dan lingkungan menciptakan Palemahan (Lemah = tanah) atau hubungan ekologis antara manusia dan alam. Orang Bali sering menggambarkan hubungan antara manusia dan alam dengan perkataan “sekadi manik ring cecupu” (seperti bayi dalam kandungan ibu). Ajaran Hindu menggambarkan alam sebagai “Ibu” yang melahirkan kehidupan (Sukadi, Februari 2007). Di sisi lain, Alam juga mendukung manusia dengan kebutuhan sehari-hari mereka untuk bertahan hidup di dunia ini, seperti halnya seorang ibu membesarkan anaknya.
Tri Hita Karana menggarisbawahi pentingnya penghormatan antara manusia dan Pencipta, alam, dan sesama manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa peran ketiga hubungan ini sebagai sistem pendukung kehidupan. Ketiga bagian ini tidak dapat diterima begitu saja, karena kelangsungan hidup manusia akan ditentukan darinya. Almarhum Ida Pedanda Made Gunung — salah satu pendeta Hindu paling terkemuka di Bali — menguraikan bahwa Tri Hita Karana akan menghasilkan tiga hubungan ideal: hubungan dengan Tuhan menciptakan bhakti (rasa hormat); hubungan dengan manusia menciptakan tresna (cinta); hubungan dengan alam menciptakan asih (welas asih). Semuanya harus dianggap sebagai integral dan harus dipenuhi sebagai satu.
Tri Hita Karana juga terkait dengan konsep “Cakra Yadnya” dari Bhagavadgita III. 16:
“Mereka yang tidak ikut memutar Roda [Cakra] Yadnya, secara timbal balik, dianggap jahat dalam sifatnya, puas hanya dengan indranya [Indria], dan, O Arjuna, akan hidup sia-sia” (Mantra, 1981, p . 44)
Kutipan ini menekankan bahwa Alam telah mengorbankan dirinya sendiri untuk manusia. Singkatnya, itu menciptakan ‘hutang’ antara manusia dan Alam / Tuhan itu sendiri yang hanya dapat dibayar dengan “Yadnya” (pengorbanan tanpa syarat). Mereka yang tidak membayar utangnya dapat digambarkan berdosa.
Konsep Tri Hita Karana kemudian mengkristal dalam beberapa praktik dalam kehidupan masyarakat Bali. Misalnya, ritual dan persembahan dalam liburan Bali adalah praktik Parahyangan. Orang Bali menunjukkan bhakti mereka kepada Ida Sang Hyang Widhi dan Dewa melalui upacara, banten, dan piodalan. Ketika mereka menyiapkan ritual, orang Bali menganggapnya sebagai kerja komunitas melalui ngayah dan gotong-royong sebagai refleksi dari filosofi Pawongan. Perilaku Parahyangan dengan demikian memperkuat ikatan sosial di Pawongan.
Praktek Pawongan terletak ketika orang Bali menjadi anggota desa pekraman di lingkungan tersebut. Desa pekraman bukan hanya badan hukum-formal, tetapi juga entitas budaya dan spiritual. Pawongan berdasarkan hukum adat yang disebut awig-awig yang berfungsi sebagai pelindung (pamikukuh) nilai-nilai tradisional dan moral di desa adat. Awig-awig adalah fondasi tidak hanya hubungan sosial, tetapi juga hubungan spiritual dengan Tuhan dan hubungan ekologis dengan alam. Dalam konteks Pawongan, hubungan sosial di desa pekraman dapat dilihat dalam praktik suka-duka dan konsep Menyama Braya (semua lelaki adalah saudara).
Terakhir, kita dapat menemukan konsep Palemahan di Subak atau sistem irigasi tradisional Bali. Sistem Subak berupaya menyeimbangkan kebutuhan manusia untuk memaksimalkan tanah dan air untuk mendukung sistem pertanian dan keberlanjutan keduanya. Sektor pertanian adalah basis untuk sektor ekonomi di Bali (selain pariwisata). Selain itu, Palemahan juga tercermin dalam praktik Tumpek Uduh — hari libur Bali untuk menghormati tanaman dan Tumpek Kandang, hari libur Bali untuk menghormati hewan.
Tri Hita Karana mencerminkan komitmen masyarakat Bali untuk menciptakan keharmonisan antara semua eksistensi yang mengelilingi mereka. I Wayan Sukarma kemudian menyimpulkan bahwa (Sukarma, 2016, p.86) :
Jika kesejahteraan menjadi cita-cita masyarakat, maka, setiap individu wajib untuk mencobanya. Upaya pertama adalah menciptakan harmoni dengan mewujudkan tatanan, regulasi, harmoni, dan keseimbangan sosial. Karena itu, ketika Tri Hita Karana menggambarkan keharmonisan dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan adalah benar-benar kekuatan, perintah, dan nasihat moral. Mengingat keharmonisan sosial tidak dapat diciptakan tanpa aturan dan moral tertentu dari mekanisme kontrol. Aturan dan kontrol moral adalah apa yang menjamin kebebasan individu dalam masyarakat. kebebasan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal yang lebih kreatif, produktif, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam konteks ini, Tri Hita Karana tidak seperti doktrin dasar dan moral Hindu yang menjadi diskusi penting dan relevan dengan kebutuhan Hindu, baik sekarang atau nanti.