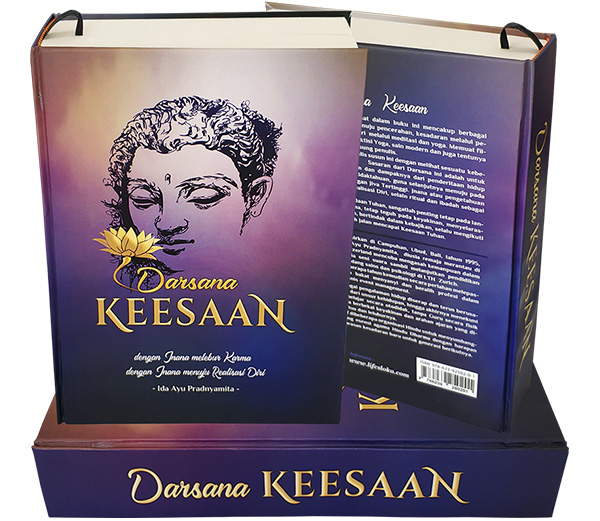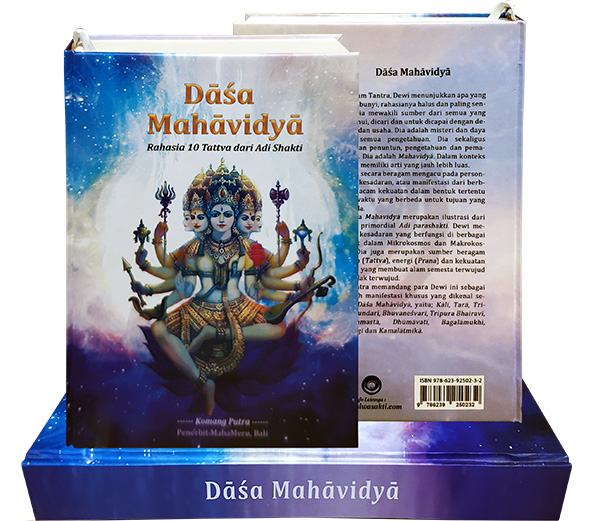Sisi Perdamaian dan Konflik “Budaya” di Bali
Pendekatan pertama dalam studi perdamaian berasal dari perspektif liberal atau dikenal sebagai “Perdamaian Liberal”. Perdamaian Liberal yang ‘mengasumsikan transformasi rangkap tiga menjadi perdamaian, demokrasi, dan ekonomi pasar adalah proses penguatan diri yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan’ (Kurtenbach 2007: 6) dan menganggap bahwa ‘demokratisasi dan liberalisasi pasar itu sendiri merupakan sumber perdamaian’ (Sriram 2007 : 579). Pendekatan perdamaian liberal memiliki kritik sendiri: terlalu tergantung pada sisi material manusia. Pemikir perdamaian liberal terlalu mengandalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi, hak politik, keadilan berbasis hukum, dan prosedur demokratis sebagai prasyarat menuju perdamaian. Di sisi lain, mereka sangat keliru memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai dalam menciptakan situasi perdamaian. Birgit Brauchler menyimpulkan bahwa:
Baik perdamaian liberal dan perangkat rekonsiliasi biasanya sejalan dengan konsep konsep Barat seperti keadilan, kebenaran, demokrasi, atau perdamaian yang mungkin secara fundamental berbeda dari nilai-nilai budaya dan pandangan dunia di wilayah lain.
Di wilayah yang masih menganggap pengaruh budaya sangat seperti Indonesia, terutama Bali, akan menjadi kesalahan besar jika kita tidak mengakui peran budaya dan nilai-nilai tradisional dalam menjaga perdamaian. Dalam penelitiannya tentang rekonsiliasi Bali setelah Bom Bali 2002, Birgit Brauchler menggarisbawahi pentingnya memperluas definisi rekonsiliasi dari konflik berbasis material dan material / nyata dari konflik, tetapi juga memberikan pemahaman tentang kepercayaan kosmologis dan agama yang lazim di daerah tersebut. yang membentuk persepsi orang tentang konflik, perdamaian, dan rekonsiliasi. Dia menambahkan bahwa:
Dalam konteks Bali, itu bukan etos global, tetapi persepsi lokal (agama) konflik dan perdamaian yang berkontribusi pada pembentukan kembali harmoni dan dengan demikian mendorong ‘rekonsiliasi’.
Brauchler menekankan bahwa nilai-nilai tradisional Bali dan Hindu memiliki kontribusi besar bagi kondisi damai yang dipertahankan di Bali setelah Bom Bali 2002. Ketika orang-orang Bali dihadapkan dengan kesengsaraan dan malapetaka Bom Bali 2002, mereka tidak terjebak dalam lingkaran kekerasan dengan menyalahkan para korban. Minoritas muslim untuk bom. Orang Bali memilih untuk merasakan bahwa Bom Bali 2002 adalah peringatan dari Tuhan karena keseimbangan dalam kosmologi spiritual Bali telah terganggu. Gangguan tersebut datang dari aspek negatif pariwisata yang membawa keserakahan kepada masyarakat Bali.
Orang Bali menafsirkan Bom Bali 2002 bukan sebagai perang antara “Baik” versus “Jahat” (seperti wacana “perang melawan teror” yang dibawa oleh Presiden AS George W. Bush) tetapi itu adalah jalan bagi kosmologi Bali untuk membawa kembali keseimbangannya. Di sisi lain, orang Bali mengakui bahwa mereka bukan hanya “korban” dan pembom Muslim adalah “pelaku”, tetapi mereka merasa bahwa mereka juga bertanggung jawab atas bom itu sendiri, terutama dalam dimensi spiritual / transendental. Singkatnya, Annette Hornbacher menyimpulkan bahwa:
Interpretasi konflik manusia ini, tidak hanya dalam hal moral tetapi dalam konteks permainan kekuatan kosmik, memiliki konsekuensi yang luas untuk gagasan orang Bali tentang tanggung jawab individu; dari sini berikut bahwa untuk pemulihan keseimbangan, tidak hanya pelaku tetapi juga korban harus bertanggung jawab, karena ia juga dianggap sebagai bagian aktif dari keseimbangan yang terganggu dan dapat membuktikan agensinya hanya dengan memperkuat kekuatan konstruktifnya dan oleh mengatasi perannya sebagai korban.
Kebutuhan Menahan Diri
Dari kasus di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan orang Bali tentang perdamaian dan perspektif Barat memiliki perbedaan. Perspektif Barat cenderung membagi perdamaian menjadi dua tingkatan: cara individu (“kedamaian batin”) dan cara sosial (“perdamaian sosial / struktural). Terlebih lagi, perspektif orang Bali menambah satu dimensi lagi: tingkat kosmologis atau juga dikenal sebagai Niskala. Niskala adalah tingkat transendental yang melengkapi sarana individu dan sosial yang dimiliki dunia material atau Sekala. Namun, keseimbangan antara Sekala dan Niskala dapat ditemukan dalam filosofi Tri Hita Karana. Tri Hita Karana termasuk individu dan masyarakat (Pawongan) sementara itu juga mengakui dimensi kosmologis (Palemahan dan Parahyangan).
Selain perbedaan antara perspektif Bali dan Barat terhadap perdamaian, keduanya memiliki kepercayaan yang sama: perdamaian dan konflik tidak bertentangan. Perspektif Bali dan Barat memiliki pemikiran yang sama bahwa konflik tidak dapat sepenuhnya hilang dari kehidupan manusia. Pandangan orang Bali tentang konflik telah dijelaskan pada bagian di atas. Namun, filosofi perdamaian Barat juga mencapai kesimpulan yang sama. Konflik adalah sisi alami yang melekat dalam kehidupan manusia. Terkait dengan pemikiran itu, Charles Webel menyimpulkan bahwa (Galtung C. W., 2007, hal. 8):
Antitesis perdamaian bukanlah konflik. Konflik nampak secara historis tidak terhindarkan dan mungkin diinginkan secara sosial jika konflik tersebut menghasilkan kemajuan pribadi dan / atau politik. Konflik mungkin, mungkin secara paradoks, mempromosikan dan meningkatkan perdamaian dan mengurangi kekerasan jika pihak yang berkonflik bernegosiasi dengan itikad baik untuk mencapai solusi untuk masalah yang dapat dicapai dan ditoleransi, jika tidak ideal.
Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa konflik memiliki fungsinya sendiri. Mungkin pahit untuk memiliki konflik, tetapi hal itu dapat membuka keluhan yang sebelumnya dimiliki seseorang. Konflik dapat memicu minat laten yang biasanya tidak dapat dilacak. Namun, jelas, konflik harus diselesaikan. Setelah konflik diselesaikan, perdamaian mungkin terjadi tetapi konflik lain mungkin muncul bahkan konflik yang sama dapat terjadi lagi. Konflik dan perdamaian adalah bagian dari kontinum melingkar dalam kehidupan manusia. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa perdamaian itu dialektis: sesuatu yang tidak statis tetapi dinamis.
Pertanyaannya kemudian: apakah itu perdamaian? Apakah kedamaian mirip dengan kebahagiaan? Charles Webel berpendapat bahwa perdamaian mungkin identik dengan kebahagiaan dalam arti sesuatu yang dicari setiap manusia dan komunitas tetapi juga tampaknya jauh untuk dicapai. Dia melanjutkan itu (Galtung C. W., 2007, hal 5-6):
Mungkin ‘perdamaian’ seperti ‘kebahagiaan’, ‘keadilan’, ‘kesehatan’ dan cita-cita manusia lainnya, sesuatu yang setiap orang dan budaya mengklaim keinginan dan memuliakan, tetapi yang sedikit jika ada mencapai, paling tidak atas dasar abadi. Mengapa kedamaian, keadilan, dan kebahagiaan begitu diinginkan, tetapi juga begitu tidak berwujud dan sulit dipahami? Tetapi mungkin perdamaian berbeda dari kebahagiaan karena tampaknya membutuhkan keharmonisan sosial dan kebebasan politik, sedangkan kebahagiaan muncul, setidaknya dalam budaya Barat, sebagian besar merupakan masalah individu.
Kedamaian juga dapat dilihat sebagai prasyarat untuk kondisi emosional. Selain itu, kondisi emosional ini cenderung menantang gangguan kognitif atau erupsi agresif. Kedamaian mungkin menyerupai kebahagiaan dalam istilah kita. Ini akan tersirat dalam pengertian psikologis kita dan juga secara sementara berlaku dalam perilaku sosial dan norma-norma budaya pria. Webel berpendapat bahwa (Galtung C. W., 2007, hal. 6):
Eros dan agresi, cinta dan benci, berbaur sejak lahir hingga dimakamkan. Memahami dan menenangkan dunia batin kita yang penuh konflik – kebutuhan kita akan dan lari dari cinta pada diri sendiri dan orang lain adalah proyek intelektual dan politik dari tatanan tertinggi dan paling mendesak. Upaya ini harus berjalan seiring dengan perlunya memahami dan mengubah konflik yang merajalela di ranah interaksi dan perpecahan interpersonal dan politik kita.
Sikap terhadap konflik adalah faktor utama di balik kondisi perdamaian. Selain itu, sikap terhadap konflik berada dalam dua lapisan: “kedamaian batin” dan “kedamaian luar”. Latar belakang psikologis seorang pria — “kedamaian batin” berbeda dari setiap orang. Itu tergantung pada faktor psikologis, karakter, dan kebiasaan. Di sisi lain, “kedamaian luar” terkait dengan norma-norma dan nilai-nilai yang memengaruhi manusia itu sendiri. Norma-norma dan nilai-nilai itu sendiri akan diinternalisasi ke dalam manusia kemudian membentuk latar belakang psikologis mereka.
“Kedamaian batin” dan “kedamaian luar” akan terhubung satu sama lain. Bahkan orang yang paling stabil pun akan menemukan kesulitan dalam menjaga dirinya stabil secara psikologis karena akan tergantung pada lingkungan. Lingkungan terutama lingkungan sosial dapat bersifat patogen. Hubungan sosial manusia dapat menekan keberadaan manusia demi menjaga kepatuhan dan ketertiban. Kedamaian luar kemudian mengikis kedamaian batin.
Di sisi lain, jika manusia merasakan kedamaian batin dengan mengikuti ego mereka, itu juga bisa mengikis kedamaian luar.
Tri Hita Karana berupaya mengatasi masalah di atas. Ego manusia sumber konflik dan kekerasan harus ditekan melalui “pengendalian diri”. Kita dapat mempelajari pentingnya “pengendalian diri” dalam menghadapi ego kita dari salah satu kutipan paling terkenal dari Mahatma Gandhi:
“Bumi menyediakan cukup untuk memuaskan kebutuhan setiap manusia, tetapi tidak semua keserakahan setiap manusia.”
Manusia harus menyadari bahwa ego dapat berdampak negatif pada kepemilikan mereka dan lingkungan mereka. Namun, orang lain dan penghuni Bumi lainnya juga memiliki hak yang sama untuk perdamaian. Jika manusia menyadari bahwa keserakahan mereka mungkin ‘memakan’ hak orang lain untuk hidup dalam damai, dan kemudian mereka harus menekannya. Harmoni adalah kunci menuju kondisi damai, dan “pengendalian diri” adalah kunci untuk memasuki kondisi damai.